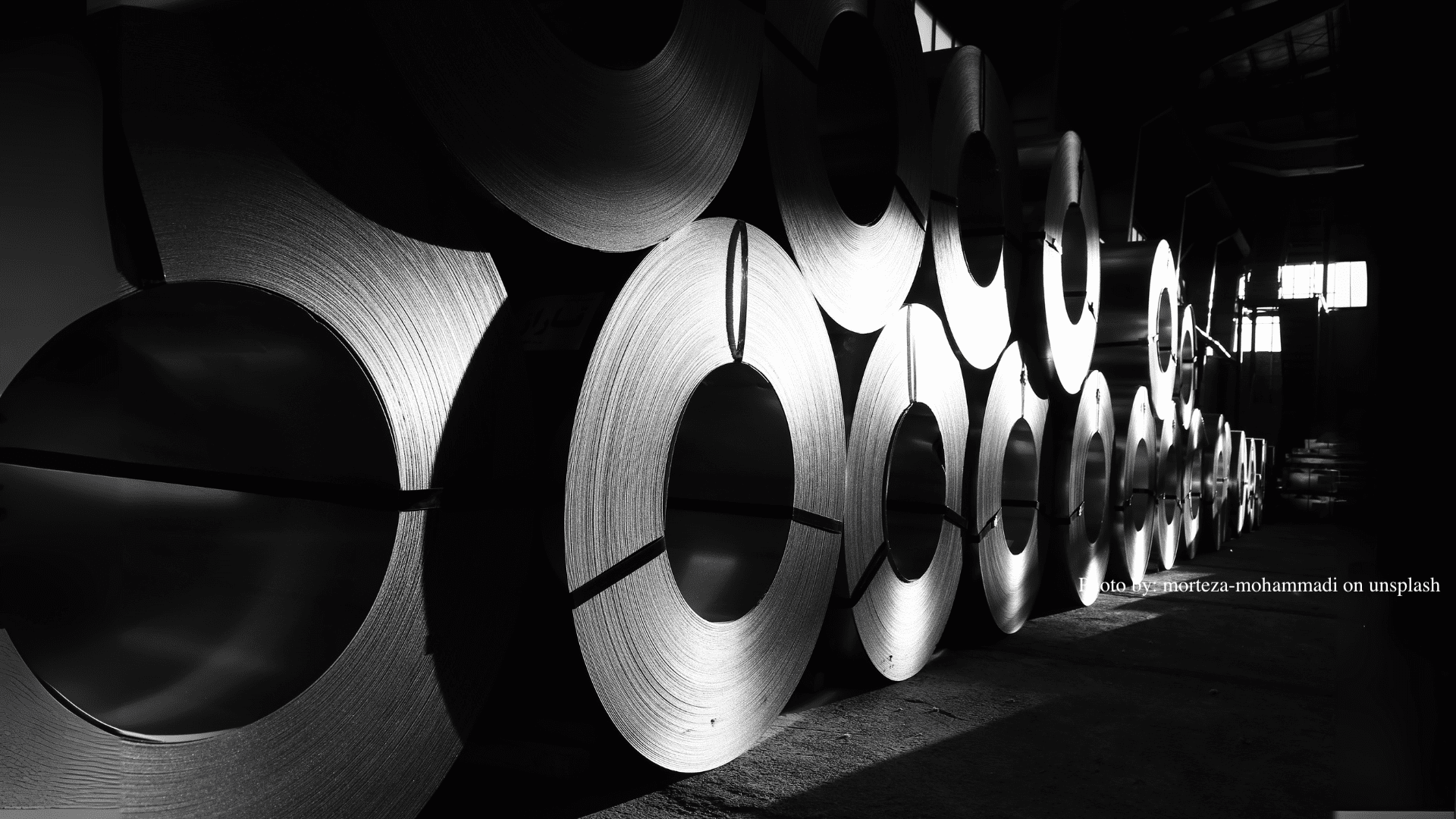Saat ini, dunia tengah bergerak menuju revolusi industri hijau—sebuah transformasi besar-besaran dari energi fosil menuju energi bersih, efisiensi, dan teknologi rendah karbon di hampir semua sektor ekonomi dalam rangka transisi emisi nol bersih (net zero emission). Perubahan ini tidak hanya menyentuh aspek teknologi dan bisnis, tetapi juga menyusun ulang peta geopolitik, arsitektur perdagangan, dan arah pembangunan ekonomi dunia. Namun di balik semangat global untuk menurunkan emisi, muncul pertanyaan mendasar: apakah semua negara harus menempuh jalan transisi yang sama dan mengikuti standar yang seragam—padahal titik awal dan kapasitas mereka sangat berbeda? Apakah jalan ini telah mencerminkan keadilan tanggung jawab, mengingat negara maju adalah penyumbang utama atas kondisi lingkungan saat ini? Apakah kebijakan global ini justru menjadi instrumen terselubung untuk mempertahankan keunggulan struktural negara maju dan menahan laju kemajuan negara berkembang? Bagaimana seharusnya transisi ini dijalankan agar tidak menjadi beban yang justru menghambat negara berkembang untuk tumbuh?
Dilema Industrialisasi Indonesia
Indonesia berada di posisi yang tidak mudah dalam menghadapi tuntutan transisi global menuju net zero emission. Di satu sisi, Indonesia sedang berada dalam fase percepatan industrialisasi dan pembangunan ekonomi yang memerlukan pasokan energi dan sumber daya yang besar, stabil, dan terjangkau. Indonesia juga memiliki kekayaan energi fosil—terutama batubara—yang selama ini menjadi tulang punggung sistem kelistrikan nasional dan dapat menjadi modal penting bagi strategi hilirisasi industri. Namun di sisi lain, tekanan internasional untuk segera meninggalkan sumber emisi tinggi terus menguat, seolah Indonesia memiliki tanggung jawab, kemampuan fiskal, infrastruktur, dan teknologi yang setara dengan negara maju. Padahal realitas di lapangan sangat berbeda: kapasitas energi terbarukan masih terbatas, kesiapan jaringan belum memadai, teknologi rendah emisi belum terjangkau, dan investasi yang dibutuhkan sangat besar di hampir semua sektor. Akibatnya, Indonesia terjebak dalam paradoks: antara memanfaatkan keunggulan energi dan sumber daya domestik untuk mengejar industrialisasi, atau memenuhi tuntutan penurunan emisi dengan mengorbankan pertumbuhan ekonomi.
Tekanan agar Indonesia segera menurunkan emisi tidak hanya mengabaikan kepentingan pertumbuhan industri Indonesia, tetapi juga melupakan dimensi historis yang menjadi akar ketimpangan iklim global. Fakta ketimpangan ini terlihat nyata ketika kita membandingkan jejak emisi kumulatif negara-negara maju dengan Indonesia. Berdasarkan data Our World in Data, sejak tahun 1850 hingga saat ini, Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menghasilkan emisi karbon kumulatif lebih dari 800 miliar ton CO, sementara Indonesia hanya sekitar 17 miliar ton—atau kurang dari 1 persen dari total global. Untuk periode 2022 hingga 2060, proyeksi dari sumber yang sama menunjukkan bahwa emisi kumulatif Indonesia diperkirakan tetap hanya sekitar 13 miliar ton, jauh di bawah Amerika Serikat (128 miliar ton) dan Uni Eropa (81 miliar ton). Meskipun kontribusinya kecil, Indonesia justru sering kali dibebani ekspektasi untuk segera menurunkan emisi secara drastis, bahkan saat ruang fiskal dan kesiapan teknologinya masih sangat terbatas.
Ketimpangan Tanggung Jawab dan Beban Transisi
Total biaya yang dibutuhkan Indonesia untuk menurunkan emisi dan mencapai target net zero pada 2060 sangat besar. Berdasarkan estimasi dari IEEFA, Bappenas, dan ADB, kebutuhan investasi untuk sektor energi dan kelistrikan saja diperkirakan mencapai USD 1 triliun. Jumlah ini masih tergolong minimal karena belum memperhitungkan biaya transisi sektor transportasi, industri, bangunan, serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Jika seluruh sektor dihitung secara sistemik menggunakan pendekatan incremental cost—yakni selisih biaya antara teknologi rendah emisi dan teknologi konvensional—total kebutuhan transisi nasional dapat melampaui USD 1,5 triliun hingga 2060. Estimasi ini merupakan hasil ekstrapolasi konservatif dari laporan Climate Policy Initiative (2023), yang mencatat kebutuhan investasi tahunan Indonesia untuk pembiayaan iklim berada di kisaran USD 243–270 miliar per tahun hingga 2030, serta laporan IEEFA (2023) yang mencatat kebutuhan investasi sektor energi mencapai USD 1 triliun hingga 2060. Selain itu, pendekatan perhitungan berbasis incremental cost juga digunakan secara konsisten dalam strategi jangka panjang pembangunan rendah karbon yang disusun Bappenas melalui kerangka Low Carbon Development Initiative (LCDI).
Jika dilihat dari nilai absolut, estimasi kebutuhan investasi Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih hingga tahun 2060 berada di kisaran USD 5–6 triliun, berdasarkan sintesis dari laporan Bappenas LCDI (2021), Kearney (2023), serta berbagai studi lain seperti IESR dan CPI. Jumlah ini sejajar dengan estimasi bawah kebutuhan Tiongkok (USD 5 triliun), meskipun ukuran ekonomi dan kapasitas fiskal kedua negara sangat berbeda. Amerika Serikat diperkirakan membutuhkan USD 10–15 triliun hingga 2050, sedangkan Uni Eropa memproyeksikan investasi tahunan sekitar USD 680 miliar hingga 2030—angka yang akan jauh lebih besar bila diperpanjang hingga 2060. Dari sisi rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), beban Indonesia bahkan lebih tinggi: Bappenas mencatat bahwa selama 2021–2030, kebutuhan investasi Indonesia setara dengan 3,4–4,5% dari PDB per tahun. Angka ini lebih besar dibandingkan rasio kebutuhan tahunan AS (2,5–3%) maupun Uni Eropa (3,7%), dan hanya sedikit di bawah Tiongkok (5–6%). Dengan kapasitas fiskal yang jauh lebih terbatas, tekanan pembiayaan Indonesia menjadi lebih berat secara struktural dibandingkan negara-negara besar tersebut.
Sebagai perbandingan, anggaran pendidikan nasional Indonesia selama lima tahun terakhir rata-rata hanya berkisar antara 3–3,5% dari PDB, sementara anggaran kesehatan bahkan lebih kecil, yaitu sekitar 1,5–2% dari PDB. Artinya, untuk memenuhi kebutuhan investasi transisi emisi sebesar 3,4–4,5% PDB per tahun, Indonesia harus mengalokasikan dana yang setara—atau bahkan lebih besar—dari seluruh anggaran pendidikan nasional, dan lebih dari dua kali lipat anggaran kesehatan. Ini bukan hanya soal skala, tetapi soal prioritas dan keterbatasan fiskal. Dalam kondisi di mana pemerintah masih perlu membiayai berbagai kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur, pembebanan transisi menuju emisi nol bersih dalam skala sebesar itu tanpa dukungan internasional yang memadai berpotensi mengorbankan agenda pembangunan nasional yang lebih mendesak bagi kesejahteraan rakyat.
Lebih jauh lagi, isu utama dari transisi emisi bukan hanya keterbatasan alokasi anggaran negara, tetapi juga dampaknya terhadap struktur biaya ekonomi nasional. Ketika peralihan menuju energi rendah karbon dijalankan secara agresif tanpa kesiapan teknologi dan dukungan fiskal yang memadai, harga energi cenderung meningkat. Kenaikan ini secara langsung mendorong biaya produksi barang dan jasa, terutama di sektor-sektor padat energi seperti industri baja, semen, pupuk, dan manufaktur berat. Akibatnya, daya saing ekspor menurun, harga barang domestik meningkat, dan tekanan inflasi menguat—yang pada gilirannya menekan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dampaknya bersifat sistemik: tidak hanya melemahkan sektor industri, tetapi juga mengganggu pasar tenaga kerja, menurunkan minat investasi swasta, dan menggerus potensi penerimaan negara. Dengan kata lain, transisi yang tidak dirancang secara kontekstual sesuai kapasitas nasional tidak hanya menjadi beban fiskal, tetapi juga ancaman nyata terhadap stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.
Namun persoalannya bukan sekadar soal besarnya biaya atau dampaknya terhadap daya saing ekonomi. Di balik tekanan global untuk segera bertransisi, tersembunyi ketimpangan historis yang menjadikan beban negara berkembang terasa tidak adil. Negara-negara maju saat ini telah mencapai tingkat pembangunan dan industrialisasi tinggi berkat pemanfaatan energi fosil secara besar-besaran selama lebih dari satu abad, dengan kontribusi emisi kumulatif yang sangat besar. Namun ketika negara berkembang seperti Indonesia sedang berada dalam fase awal industrialisasi dan masih membutuhkan energi murah dan andal, justru diminta untuk menempuh jalur pembangunan yang lebih mahal melalui energi bersih dan teknologi rendah emisi. Ketimpangan inilah yang menimbulkan tuntutan agar skema transisi global disusun secara lebih adil dan proporsional. Janji pendanaan sebesar USD 100 miliar per tahun yang telah disepakati sejak COP15 di Kopenhagen pada 2009 belum pernah benar-benar terealisasi, dan jika pun tercapai, tetap jauh dari cukup. Sementara itu, menurut estimasi Kearney, Indonesia membutuhkan paling tidak USD 2,4 triliun untuk mendanai transisi menuju net zero hingga 2060—setara dengan rata-rata USD 61,5 miliar per tahun. Artinya, kebutuhan tahunan Indonesia saja mencapai lebih dari 60 persen dari total komitmen global negara maju yang ditujukan bagi seluruh negara berkembang. Dan sebagian besar beban ini harus ditanggung sendiri melalui APBN, BUMN, dan sektor swasta domestik yang kapasitasnya terbatas. Tanpa dukungan pendanaan internasional yang kuat dan berkelanjutan, transisi menuju emisi nol bersih yang diharapkan justru dapat memperlebar ketimpangan pembangunan antara negara maju dan berkembang.
Ketidakadilan lainnya muncul dari fakta bahwa banyak fasilitas dan aset industri di negara berkembang masih tergolong baru, sementara di negara maju umumnya sudah tua dan mendekati akhir masa pakainya. Dengan demikian, transisi menuju teknologi rendah emisi di negara maju cenderung lebih alami karena mereka memang harus mengganti infrastruktur yang sudah usang. Sebaliknya, di negara berkembang seperti Indonesia, banyak instalasi industri—termasuk pembangkit listrik dan fasilitas manufaktur—masih baru dan belum menyentuh usia keekonomian penuh. Misalnya, teknologi tanur tiup (blast furnace) di Eropa telah beroperasi selama beberapa dekade dan kini secara bertahap digantikan oleh teknologi berbasis hidrogen. Sementara di Indonesia, fasilitas serupa baru dibangun dalam kurun waktu 5–10 tahun terakhir. Jika dipaksa untuk segera bermigrasi ke teknologi baru, Indonesia tidak hanya kehilangan potensi pemanfaatan aset yang masih produktif, tetapi juga harus menanggung biaya transisi yang jauh lebih tinggi. Dalam konteks ini, prinsip keadilan transisi semestinya mencakup dimensi umur infrastruktur dan siklus investasi, bukan hanya target emisi yang bersifat absolut.
Karena itu, bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, transisi menuju sistem rendah emisi tidak bisa dijalankan secara seragam dengan negara maju. Pendekatan yang diambil harus mempertimbangkan konteks pembangunan, struktur ekonomi, dan umur aset yang dimiliki. Alih-alih sekadar menyalin target atau jalur dekarbonisasi negara maju, Indonesia perlu merumuskan strategi transisi yang bertahap dan adaptif—yang tidak hanya menurunkan emisi, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing. Prinsip ini juga sejalan dengan pendekatan yang dikedepankan dalam berbagai forum internasional seperti G20 dan COP, yaitu bahwa transisi harus adil, terjangkau, dan tidak meninggalkan siapa pun di belakang (no one left behind). Tanpa strategi nasional yang kontekstual, Indonesia justru berisiko kehilangan momentum pembangunan hanya demi memenuhi ekspektasi global yang belum tentu mencerminkan kepentingan domestik.
Jalan Transisi Indonesia Menuju Emisi Nol Bersih
Di tengah kompleksitas tersebut, semakin banyak suara dari kalangan pembuat kebijakan dan tokoh nasional yang mempertanyakan relevansi Indonesia untuk tetap terikat penuh pada skema dan target yang ditetapkan dalam kerangka Paris Agreement, terutama jika negara-negara besar seperti Amerika Serikat sendiri tidak konsisten dalam komitmennya. Pernyataan Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Bidang Iklim, menggambarkan kegelisahan itu dengan tajam: “Kalau AS yang saat ini merupakan pencemar kedua terbesar setelah China tidak mau mematuhi nuruti perjanjian internasional, kenapa harus negara seperti Indonesia harus patuhi,” tuturnya dalam CNBC Indonesia ESG Sustainability Forum 2025 di Jakarta, Jumat (31/1/2025). Sikap kritis semacam ini mencerminkan perlunya evaluasi ulang terhadap posisi Indonesia dalam arsitektur transisi global—bukan untuk mundur dari komitmen iklim, tetapi untuk memastikan bahwa jalur transisi yang ditempuh benar-benar mencerminkan kepentingan nasional, kapasitas aktual, dan prinsip keadilan internasional.
Ke depan, strategi transisi Indonesia perlu dirancang secara bertahap, terukur, dan terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk mengabaikan komitmen penurunan emisi, tetapi justru memastikan bahwa transisi dilakukan secara berkelanjutan, adil, dan sesuai dengan kapasitas domestik. Prioritas awal dapat diarahkan pada sektor-sektor yang telah memiliki kesiapan teknologi dan struktur pembiayaan yang lebih kuat, sambil tetap mendorong penguatan kapasitas pada sektor-sektor lain yang memerlukan waktu lebih panjang untuk bertransformasi. Dengan demikian, transisi dapat menjadi bagian dari solusi pembangunan—bukan hambatan. Pendekatan semacam ini juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional, sebagai negara yang serius menjalankan transisi, namun tetap mengedepankan prinsip keadilan dan relevansi nasional.
Di tengah tekanan global untuk mempercepat penurunan emisi dan desakan domestik untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, Indonesia dihadapkan pada pilihan strategis yang tak mudah. Menurunkan emisi jelas penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi pertumbuhan industri juga tak kalah krusial untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Karena itu, pilihan yang harus diambil bukanlah sekadar “penurunan emisi atau pertumbuhan,” tetapi bagaimana menempuh jalan tengah yang adil dan kontekstual: membangun industri yang tetap tumbuh, namun secara bertahap bergerak ke arah yang lebih bersih. Strategi transisi yang cermat—berbasis kapasitas domestik, keberlanjutan fiskal, dan dukungan internasional yang nyata—merupakan kunci agar Indonesia tidak hanya menjadi korban dari arsitektur transisi global, tetapi juga menjadi pelaku utama yang menentukan arah masa depannya sendiri.
Artikel ini telah tayang di Kompasiana, klik untuk baca di Kompasiana: https://www.kompasiana.com/widodosetiadarmaji5795/683e5c18ed6415629f22d452/penurunan-emisi-atau-pertumbuhan-menimbang-arah-industrialisasi-indonesia
Widodo Setiadharmaji adalah pendiri SMInsights dengan pengalaman lebih dari dua puluh tahun dalam bidang teknologi, strategi bisnis, dan pengembangan industri. Penulis artikel dinamika dan kebijakan industri yang dipublikasikan di Kompas, KataData, dan media nasional lainnya.