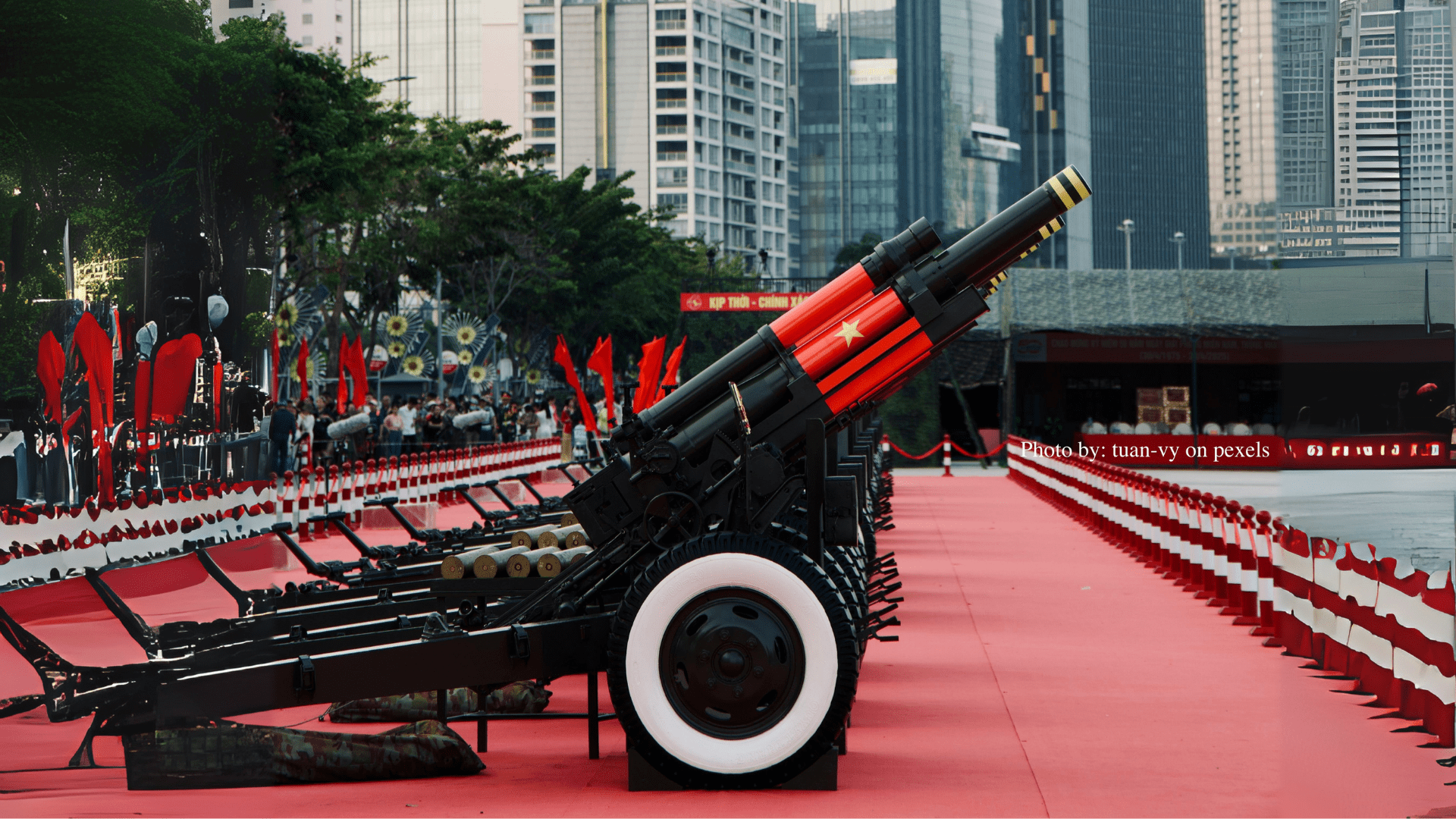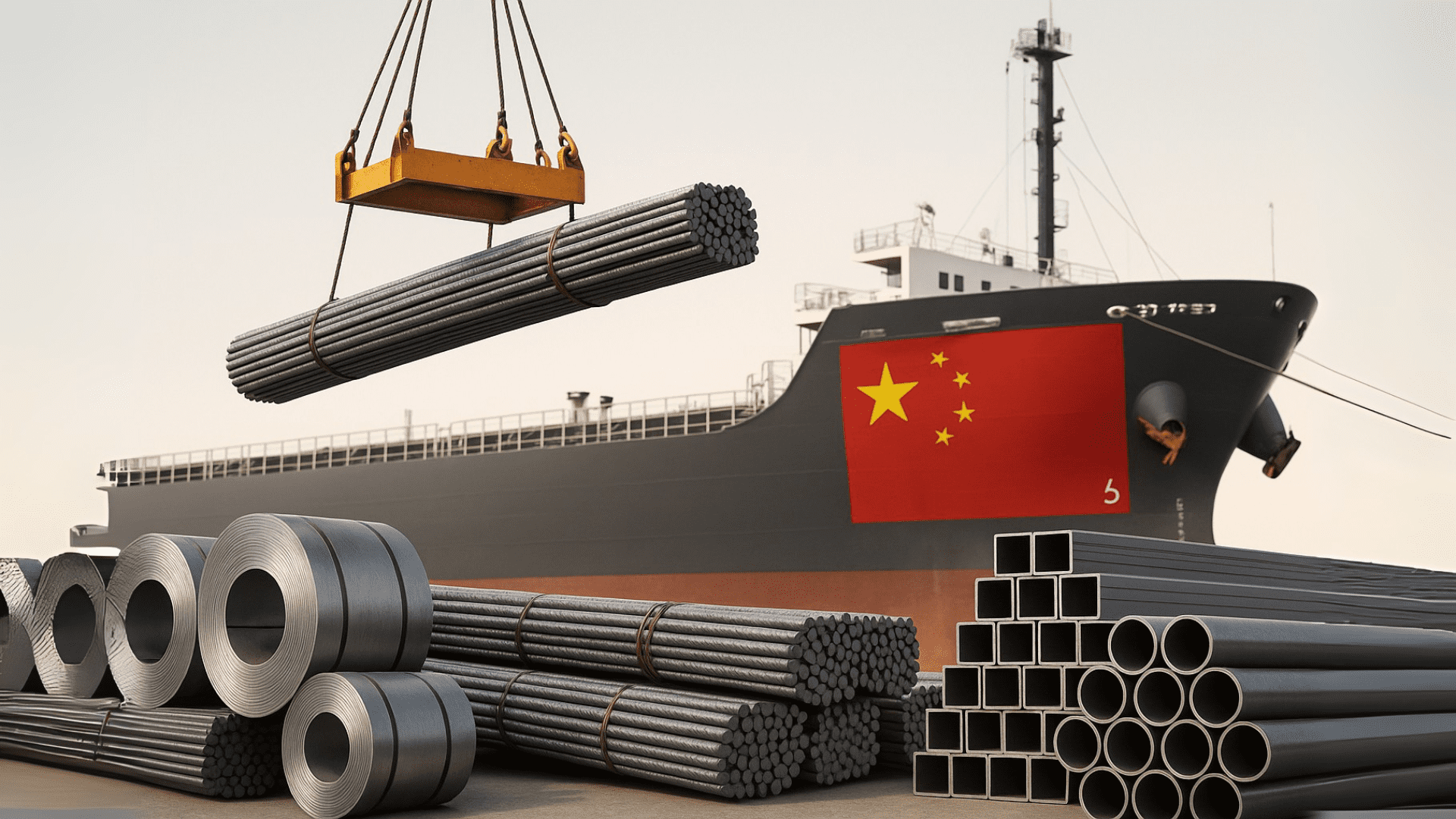Pada 2 April 2025, Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump kembali memberlakukan tarif impor secara luas terhadap produk manufaktur dari hampir seluruh negara. Vietnam termasuk yang paling terdampak, dengan tarif resiprokal tertinggi sebesar 64%, akibat defisit perdagangan bilateral yang besar—mencapai USD 123,5 miliar pada 2024—dan posisinya sebagai eksportir manufaktur utama ke pasar AS. Perbedaan tarif dan defisit neraca perdagangan ini menjadi indikator ketimpangan struktur industri antara kedua negara, yang juga terlihat dari disparitas volume ekspor manufakturnya. Data U.S. Census Bureau (2024) menunjukkan bahwa nilai ekspor manufaktur Vietnam ke Amerika Serikat mencapai US$136,6 miliar, hampir lima kali lipat lebih besar dibandingkan ekspor Indonesia ke pasar yang sama sebesar US$28,1 miliar. Padahal pada awal 2000-an, Indonesia sempat lebih unggul dalam ekspor produk manufaktur seperti tekstil, furnitur, dan alas kaki ke pasar Amerika (US Census Bureau, 2022).
Keunggulan Vietnam atas Indonesia tidak hanya terjadi di pasar AS, tetapi juga terlihat secara global. Total ekspor Vietnam pada 2024 mencapai USD 405,53 miliar, jauh melampaui Indonesia yang hanya mencatat ekspor sebesar USD 264,70 miliar (GSO Vietnam, BPS, 2024). Namun lebih dari sekadar selisih nilai, perbedaan paling mencolok terletak pada struktur ekspor kedua negara. Ekspor Vietnam didominasi oleh produk manufaktur, yang menyumbang lebih dari 90% dari total ekspor nasional mereka (GSO Vietnam, 2024). Sebaliknya, struktur ekspor Indonesia masih sangat bergantung pada bahan baku mentah dan produk olahan primer berbasis sumber daya alam yang diperkirakan mencapai sekitar 62–65% dari total ekspor nasional (BPS, 2024). Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah menjalankan kebijakan hilirisasi selama lebih dari satu dekade, perekonomian nasional belum sepenuhnya bertransformasi menuju basis manufaktur yang kuat dan berdaya saing global—seperti yang telah dicapai Vietnam.
Situasi ini memunculkan pertanyaan strategis: mengapa Vietnam dapat melesat dalam industrialisasi tanpa berbasis sumberdaya alam, sementara Indonesia yang telah memanfaatkan sumberdaya alam melalui kebijakan hilirisasi malah tertinggal? Jawabannya terletak pada perbedaan mendasar dalam orientasi dan strategi. Hilirisasi memang penting, tetapi hanya akan berdampak jika menjadi bagian dari industrialisasi yang menyeluruh—yang mencakup produktivitas tenaga kerja, keterhubungan logistik, insentif investasi, serta integrasi dalam rantai pasok global. Vietnam unggul dalam seluruh aspek tersebut.
Sejarah Industrialisasi Indonesia
Indonesia sebenarnya bukan tanpa sejarah industrialisasi. Di era Orde Baru, strategi substitusi impor dijalankan melalui pembangunan industri strategis nasional di sektor minyak dan gas, petrokimia, baja dan logam dasar, otomotif, serta tekstil—yang menjadi pilar utama manufaktur nasional pada saat itu. Masa keemasan sektor manufaktur terjadi antara 1985–2000, ketika kontribusinya terhadap PDB nasional menembus 29%. Produk manufaktur Indonesia mulai mendominasi ekspor nonmigas, dengan kontribusi utama berasal dari sektor tekstil dan garmen, elektronik, alas kaki, produk kayu, serta komponen otomotif—yang secara kolektif membentuk lebih dari separuh total ekspor nonmigas nasional pada dekade 1990-an (World Bank, 2010).
Namun, pasca krisis ekonomi 1998, arah industrialisasi Indonesia memasuki masa stagnasi. Reformasi struktural tidak diiringi dengan konsistensi kebijakan industri. Kontribusi manufaktur terhadap PDB terus merosot, dari sekitar 29% pada 2001 menjadi hanya 18,7% pada 2023 (BPS, 2024). World Bank mencatat bahwa sejak 2012, Indonesia telah memasuki fase deindustrialisasi dini, yaitu penurunan proporsi sektor manufaktur terhadap PDB yang terjadi sebelum negara tersebut mencapai tingkat pendapatan menengah-atas (World Bank, 2014).
Stagnasi ini bukan hanya kuantitatif. Secara kualitatif, struktur industri Indonesia terjebak pada produk bernilai tambah rendah dan padat karya murah, seperti pakaian jadi, sepatu olahraga, dan furnitur sederhana—yang meskipun menyerap tenaga kerja besar, memiliki margin rendah dan rentan terhadap relokasi industri. Belum terjadi lompatan signifikan ke sektor industri dengan nilai tambah menengah-tinggi—seperti permesinan, kimia industri, elektronik, peralatan medis, semikonduktor, hingga komponen otomotif presisi—yang umumnya memerlukan penguasaan teknologi, R&D, serta proses produksi dengan toleransi presisi tinggi (World Bank, 2021).
Ada sejumlah masalah yang berimbas deindustrialisasi di Indonesia. Pertama, regulasi industri yang tidak stabil dan tumpang tindih. Studi World Bank (2024) mencatat bahwa Indonesia tertinggal dari Vietnam dalam hal “regulatory quality” dan “contract enforcement”. Sementara itu, dalam IMD World Competitiveness Yearbook 2023, Indonesia memang berada di peringkat lebih tinggi dari Vietnam (34 berbanding 40), tetapi laporan JICA (2023) World Bank B-READY (2023) menunjukkan bahwa efektivitas perizinan, kepastian kebijakan industri, serta kecepatan layanan investasi masih menjadi keunggulan utama Vietnam di mata pelaku usaha. Laporan B-READY juga menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan industri di Indonesia.
Kedua, iklim hubungan industrial yang rapuh. Aksi demonstrasi buruh masih kerap terjadi di berbagai kawasan industri, terutama di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat, dipicu oleh ketidakpastian hubungan kerja dan kasus pemutusan hubungan kerja massal. Ketidakpastian sosial semacam ini menjadi disinsentif bagi industri yang mengandalkan stabilitas tenaga kerja.
Ketiga, efektivitas insentif investasi yang masih terbatas. PMK No. 69/2024 sebenarnya memberikan tax holiday hingga 20 tahun untuk investasi strategis, namun berbagai evaluasi seperti OECD Investment Policy Review (2020) dan laporan Kemenko Perekonomian (2021) menunjukkan bahwa prosedur pengajuan insentif masih rumit, tidak otomatis, dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pengembangan kawasan industri. Kemenko Perekonomian juga menetapkan target penyelesaian kebijakan insentif fiskal yang berkualitas sebesar 90% (Program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2024). Terobosan ini menunjukkan adanya perbaikan desain kebijakan, meskipun tantangan implementasi di lapangan masih perlu terus diatasi agar skema insentif benar-benar mendukung daya saing kawasan industri secara komprehensif. Keterbatasan efektivitas insentif juga tercermin dari rendahnya rasio investasi asing langsung terhadap PDB Indonesia, yang hanya sekitar 1,6%, jauh di bawah Vietnam yang telah mencapai lebih dari 4% dari PDB. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya kuantitas, tetapi kualitas dan efisiensi pemanfaatan insentif menjadi pembeda penting antara kedua negara.
Keempat, iklim keamanan usaha yang belum sepenuhnya kondusif. Di beberapa kawasan industri, isu premanisme dan intimidasi terhadap pelaku usaha masih menjadi keluhan utama investor, terutama yang bergerak di sektor padat modal dan membutuhkan stabilitas operasional jangka panjang. Fenomena ini kembali mencuat ke permukaan dalam berbagai laporan media sepanjang 2024–2025, dengan sejumlah kasus kekerasan, pungutan liar, dan intimidasi yang mengganggu proses logistik dan distribusi. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah hukum dalam beberapa kasus, akar persoalan ini berkaitan erat dengan lemahnya penegakan hukum di tingkat lokal dan belum optimalnya sinergi antara aparat keamanan, otoritas kawasan industri, dan pelaku usaha. Ketidakpastian semacam ini menambah beban risiko investasi di Indonesia dan mereduksi daya saing kawasan industri nasional dibanding negara pesaing seperti Vietnam, yang lebih dikenal sebagai lokasi manufaktur dengan tingkat gangguan keamanan yang rendah. Kelima, kawasan industri dan logistik yang tidak terintegrasi. Studi Kementerian Perindustrian (2022) dan World Bank (2023) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil kawasan industri di Indonesia yang memiliki akses langsung ke pelabuhan laut dalam atau jaringan moda logistik terpadu. Sebagian besar kawasan industri nasional belum dilengkapi dengan infrastruktur pendukung seperti jalan penghubung, jaringan utilitas stabil, serta pusat logistik yang terintegrasi. Hal ini menyebabkan biaya logistik Indonesia tetap tinggi—mencapai sekitar 23,5% dari PDB menurut World Bank dan ALFI (2023)—jauh di atas Vietnam yang hanya sekitar 16,8% menurut estimasi World Bank. Selain itu, Vietnam mencetak peringkat lebih baik dalam Logistics Performance Index (LPI) 2023, yakni posisi 39 dari 160 negara, sedangkan Indonesia berada di peringkat 63. Perbedaan ini mencerminkan efisiensi sistem logistik Vietnam yang lebih kompetitif secara global. Selisih biaya logistik ini sangat mempengaruhi daya saing manufaktur, terutama dalam industri berorientasi ekspor.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Menapak Jejak Vietnam, Membangun Kembali Industri Indonesia (Bagian I)”, Klik untuk baca di Kompas: https://money.kompas.com/read/2025/04/20/083658726/menapak-jejak-vietnam-membangun-kembali-industri-indonesia-bagian-i.
Widodo Setiadharmaji adalah pendiri SMInsights dengan pengalaman lebih dari dua puluh tahun dalam bidang teknologi, strategi bisnis, dan pengembangan industri. Penulis artikel dinamika dan kebijakan industri yang dipublikasikan di Kompas, KataData, dan media nasional lainnya.