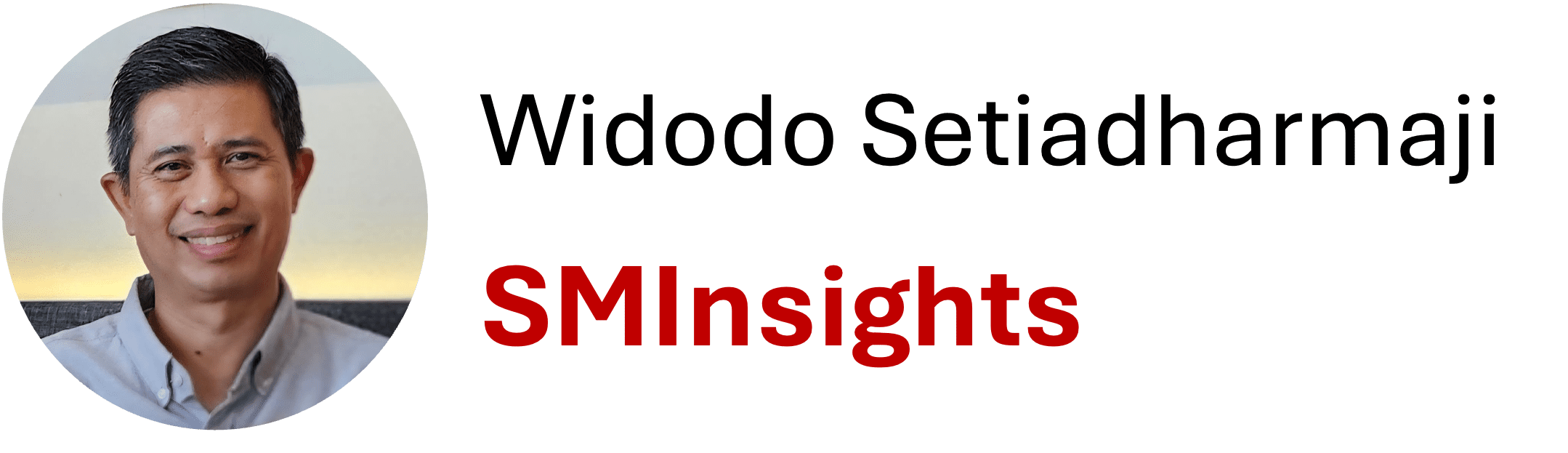
Industri baja Inggris kini menghadapi tekanan yang sangat berat. Dua pemain utama, Tata Steel UK dan British Steel, sama-sama berada dalam kondisi kritis akibat perlindungan perdagangan yang tidak memadai, menurunnya daya saing akibat lonjakan biaya produksi, dan kegagalan menyesuaikan diri dengan tuntutan transisi energi. Pada April 2024, Tata Steel UK akhirnya menerima intervensi pemerintah melalui suntikan dana publik demi menjaga kelangsungan operasional pabrik Port Talbot dan menyelamatkan ribuan tenaga kerja. Sementara itu, British Steel masih terus bergulat dengan risiko penutupan fasilitas produksi karena ketidakpastian pendanaan. Situasi ini mencerminkan bahwa krisis yang terjadi bukan semata permasalahan individual korporasi, melainkan akibat tekanan struktural yang dihadapi industri baja Inggris secara keseluruhan—terutama dari banjir impor baja murah dari berbagai negara yang memiliki kelebihan kapasitas, termasuk Tiongkok—yang memerlukan kehadiran negara untuk mencegah kehancuran total.
Kondisi ini bukanlah hasil dari satu keputusan keliru, melainkan akumulasi dari kebijakan liberalisasi yang mengabaikan pentingnya industri strategis. Ketika negara-negara seperti Amerika Serikat, India, dan Tiongkok memperkuat basis industrinya dengan proteksi dan insentif, Inggris justru membiarkan sektor bajanya terpapar tekanan pasar global tanpa perlindungan yang memadai. Kejatuhan ini menjadi pengingat bagi negara berkembang seperti Indonesia bahwa tidak ada negara industri kuat tanpa fondasi industri baja yang tangguh.
Indonesia dalam Dilema
Bagi Indonesia, krisis industri baja Inggris harus menjadi cermin reflektif sekaligus peringatan dini. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen per tahun, dan ambisi menjadi kekuatan industri baru pada 2045, Indonesia tidak mungkin lepas dari kebutuhan akan baja dalam skala masif. Saat ini, kapasitas produksi baja nasional masih berkisar di bawah 20 juta ton per tahun, dengan tingkat utilisasi pabrik yang belum optimal. Proyeksi kebutuhan baja Indonesia pada 2045 bahkan diperkirakan mencapai 100 juta ton per tahun jika seluruh agenda pembangunan industri, infrastruktur, dan manufaktur berjalan sesuai rencana.
Namun di tengah proyeksi kebutuhan yang besar tersebut, Indonesia justru menghadapi kenyataan paradoks: lebih dari 40 persen konsumsi baja domestik masih dipenuhi oleh impor, meskipun secara nominal kapasitas produksi dalam negeri telah mencukupi. Artinya, kita tidak hanya menghadapi masalah kekurangan pasokan, tetapi masalah struktural berupa kelebihan kapasitas yang tidak produktif dan utilisasi pabrik yang sangat rendah. Sebagian besar pabrik baja nasional tidak mampu bersaing bukan semata karena faktor biaya produksi dan kualitas, melainkan adanya praktik perdagangan curang (unfair trade practices) termasuk subsidi besar-besaran Tiongkok. Dalam kondisi seperti ini, industri domestik yang tidak dilindungi oleh kebijakan negara akan selalu kalah dari produk impor murah yang dijual di bawah harga keekonomian disertai praktik perdagangan curang berupa produk tidak standar dan penghindaran bea masuk melalui circumvention.
Tanpa sistem perlindungan yang memadai, kebijakan peningkatan kapasitas justru akan menciptakan overhang struktural dan mendorong industri baja nasional ke dalam krisis berulang—sebagaimana yang dialami oleh Tata Steel UK dan British Steel.
Kondisi ini menempatkan Indonesia pada titik dilema strategis. Di satu sisi, industri baja nasional sedang terlilit masalah struktural yang kompleks. Tapi di sisi lain, jika tidak disiapkan dari sekarang, Indonesia berisiko besar menghadapi lonjakan kebutuhan baja dalam 20 tahun ke depan dengan ketergantungan penuh pada impor. Tanpa transformasi yang tepat dan terarah, Indonesia akan mengulangi kesalahan Inggris—kehilangan kedaulatan industri baja karena gagal memberikan perlindungan dan dukungan yang memadai bagi ketahanan dan pertumbuhan jangka panjang.
Keharusan Proteksi
Pelajaran dari Inggris sangat jelas: liberalisasi total tanpa strategi protektif akan mengakibatkan deindustrialisasi. Sejak privatisasi dan deregulasi besar-besaran pada 1980-an, industri baja Inggris mengalami penurunan investasi, stagnasi teknologi, dan pelemahan posisi pasar. Ketika arus ekspor baja murah dari China membanjiri pasar global setelah 2000-an, industri Inggris yang tidak lagi dilindungi, tergerus habis oleh persaingan harga. Tidak adanya intervensi strategis membuat mereka kalah bukan karena kekurangan pasar, tetapi karena harus berhadapan dengan impor berharga sangat rendah akibat subsidi dan praktik dumping. Ironisnya, ketika banyak negara kini memperkuat sistem perlindungan industrinya, Indonesia malah tengah merancang kebijakan yang berpotensi menghapus pembatasan impor dan melonggarkan kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)—sebuah arah kebijakan yang, jika diterapkan tanpa pertimbangan dan rencana strategis komprehensif, sangat mungkin mempercepat proses deindustrialisasi seperti yang dialami Inggris.
Sebaliknya, negara-negara yang berhasil mempertahankan industrinya mengambil langkah tegas dan terarah. Instrumen trade remedies menjadi pilihan utama yang digunakan secara luas di tingkat global. Amerika Serikat, misalnya, menerapkan tarif baja sejak 2018 dan memperluasnya melalui Liberation Day Tariff pada 2025—sebuah kebijakan yang kemudian diikuti oleh hampir semua negara produsen baja utama. Dalam konteks transisi energi, mereka tidak membiarkan industrinya runtuh, melainkan memfasilitasi transformasi ke arah baja hijau melalui pendanaan riset, dukungan hidrogen, dan relokasi teknologi emisi rendah.
Indonesia belum terlambat, tetapi tidak punya banyak waktu. Strategi pembangunan industri baja ke depan harus dimulai dari pengakuan bahwa industri ini adalah sektor yang sangat strategis—the mother of all industries—karena menjadi fondasi dari seluruh ekosistem industrialisasi: konstruksi, otomotif, perkapalan, pertahanan, alat berat, manufaktur, logistik, hingga energi. Namun pengakuan tersebut tidak cukup jika tidak diikuti dengan langkah nyata. Di India, keberadaan Kementerian Baja memperlihatkan keseriusan negara dalam mengelola sektor ini sebagai prioritas nasional. Di Tiongkok, pembangunan ekosistem riset dan inovasi baja dilakukan melalui jaringan lembaga teknologi dan kemitraan negara-korporasi yang solid. Indonesia perlu membangun kerangka kelembagaan dan kebijakan yang berpihak secara eksplisit pada penguatan industri baja nasional. Membangun industri baja yang kuat tidak bisa diserahkan pada pelaku usaha semata—kondisi krisis di Inggris telah membuktikan risikonya. Negara harus hadir dengan memberikan perlindungan terhadap pasar domestik dari praktik perdagangan curang, mendukung investasi kapasitas baru yang terarah dan sesuai kebutuhan nasional melalui insentif yang kompetitif, dan membenahi struktur biaya produksi secara nasional agar industri baja benar-benar siap menghadapi tantangan global dan mendukung pertumbuhan jangka panjang.
Kegagalan Inggris mempertahankan industrinya membuktikan bahwa ketika negara memilih untuk tidak bertindak, itu sama saja dengan membiarkan industri nasional dihancurkan oleh kekuatan pasar global. Ketika negara tidak hadir untuk membangun daya saing strategis, maka pasar global akan mengambil alih dan menghapus industri yang tak mampu bersaing. Bagi Indonesia, tantangan ini harus dijawab dengan pendekatan sistemik: menyatukan kebijakan perdagangan, energi, investasi, dan teknologi dalam satu peta jalan industri baja nasional.
Sebagai negara berkembang yang bercita-cita menjadi negara maju, Indonesia tidak boleh kehilangan industri baja seperti Inggris. Justru, dalam konteks geopolitik global yang semakin fragmentaris dan era proteksionisme baru, kemandirian industri adalah fondasi dari kedaulatan ekonomi.
Industri baja bukan sekadar bisnis logam. Ia adalah simbol kemampuan negara membangun, memproduksi, dan berdiri di atas kaki sendiri. Dan untuk itu, negara harus hadir. Bukan untuk menggantikan pasar, tetapi untuk mengarahkan dan melindungi agar pasar bekerja bagi kepentingan nasional jangka panjang. Pada akhirnya, persaingan industri baja global bukan lagi ditentukan oleh keunggulan perusahaan, tetapi oleh kekuatan kebijakan negara. Siapa yang memiliki strategi, keberpihakan, dan keberanian untuk melindungi serta membangun industrinya—dialah yang akan bertahan.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Krisis Industri Baja Inggris: Pelajaran bagi Indonesia”, Klik untuk baca di Kompas: https://money.kompas.com/read/2025/04/17/080000426/krisis-industri-baja-inggris–pelajaran-bagi-indonesia.
Widodo Setiadharmaji adalah pendiri SMInsights dengan pengalaman lebih dari dua puluh tahun dalam bidang teknologi, strategi bisnis, dan pengembangan industri. Penulis artikel dinamika dan kebijakan industri yang dipublikasikan di Kompas, KataData, dan media nasional lainnya.



