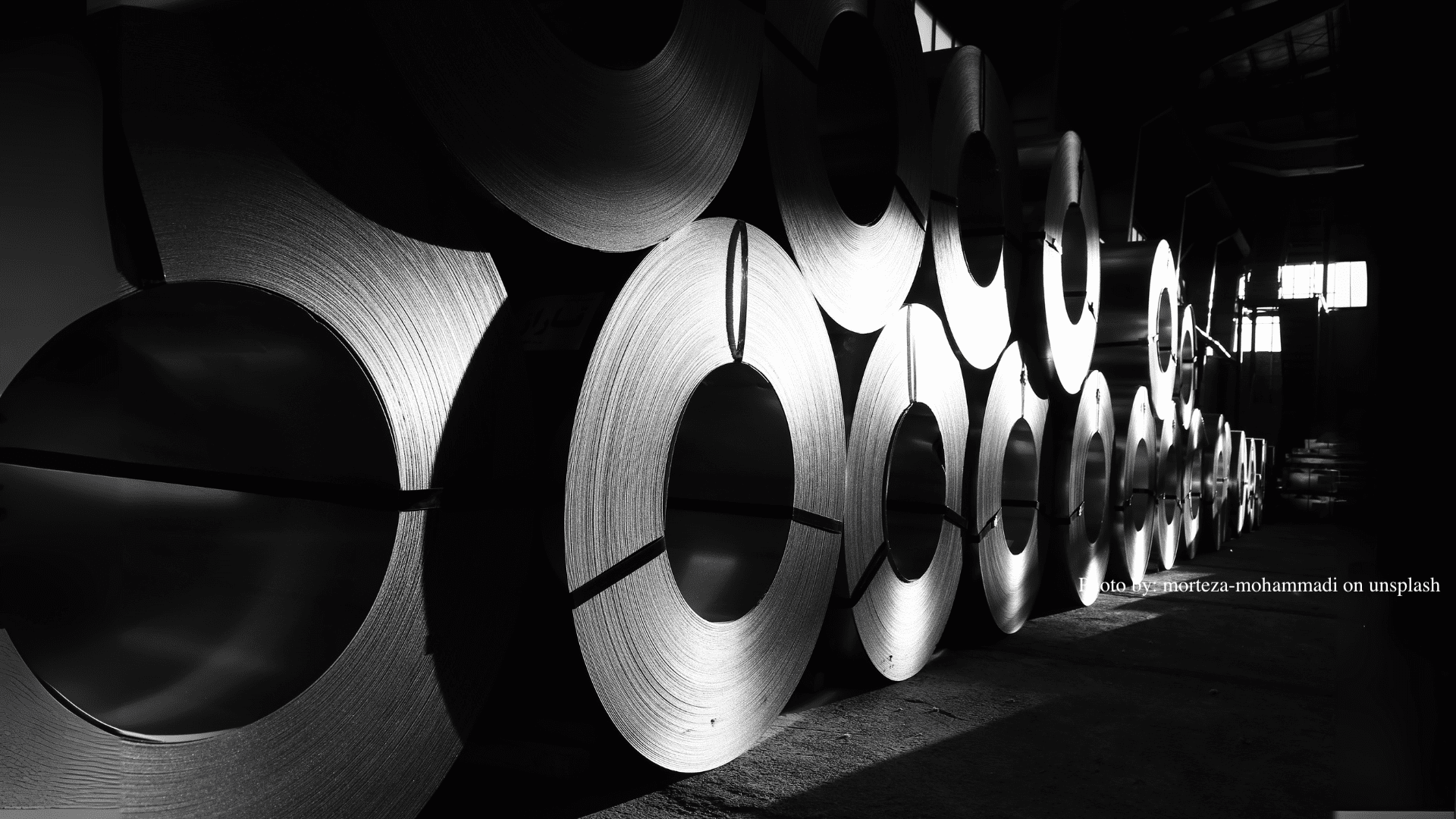Isu kelebihan kapasitas baja dan distorsi kebijakan global kembali menjadi sorotan dalam pertemuan Global Forum on Steel Excess Capacity (GFSEC) yang berlangsung pada Oktober 2025 di Gqeberha, Afrika Selatan. Forum ini memperingatkan bahwa krisis overcapacity global kian memburuk, diperparah oleh praktik subsidi dan ekspor murah yang mengancam keberlangsungan industri baja nasional di banyak negara. Bagi Indonesia, sinyal peringatan tersebut telah menampakkan wujud nyatanya.
Pada 25 Agustus 2025, PT Ispat Indo resmi menutup seluruh operasional pabriknya di Sidoarjo. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya tampak sebagai keputusan bisnis biasa. Namun bagi siapa pun yang memahami sejarah dan struktur industri baja nasional, penutupan ini menyiratkan sesuatu yang jauh lebih serius: sebuah pabrik baja nasional yang telah beroperasi sejak 1976—dan menjadi titik awal lahirnya raksasa global ArcelorMittal—ditutup karena tidak lagi mampu bertahan di tengah pasar yang terus tumbuh di negara yang justru diproyeksikan menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat atau kelima dunia pada tahun 2050.
Ispat Indo bukan pemain kecil. Dengan kapasitas produksi lebih dari 700.000 ton per tahun, perusahaan ini selama puluhan tahun menjadi bagian penting dari rantai pasok konstruksi nasional. Lebih dari itu, di belakangnya berdiri ArcelorMittal—produsen baja terbesar di dunia—dengan volume produksi mencapai 57,9 juta ton pada 2024, atau lebih dari tiga kali total kebutuhan baja nasional Indonesia. Dalam dua tahun terakhir, ArcelorMittal aktif memperluas investasinya secara agresif: dari akuisisi senilai USD 2,2 miliar di Brasil, ekspansi terintegrasi di India dan Kanada, hingga pembangunan fasilitas baja listrik dan non-grain oriented electrical steel (NOES) di Amerika Serikat dengan nilai hampir USD 1 miliar. Di negara-negara tersebut, kepastian kebijakan dan dukungan jangka panjang menjadi faktor utama pendorong keputusan investasi. Sebaliknya, di Indonesia—pasar baja terbesar di Asia Tenggara—pabrik historis yang pernah menjadi bagian awal ekspansi global ArcelorMittal justru harus ditutup. Pertanyaannya, apakah Indonesia belum memiliki arsitektur kebijakan dan instrumen perlindungan yang sepadan di tengah memburuknya distorsi pasar baja global?
Gelombang Tantangan yang Meruntuhkan Ispat Indo
Industri baja global telah mengalami kelebihan kapasitas secara akut sejak beberapa tahun terakhir, dengan estimasi overcapacity global mencapai lebih dari 600 juta ton per tahun menurut data OECD dan GFSEC. Kelebihan kapasitas terbesar terutama terjadi di Tiongkok, yang kemudian mendorong ekspor besar-besaran ke pasar global. Berdasarkan berbagai laporan internasional, Alert, ekspor ini dilakukan dengan dukungan menyeluruh dari pemerintah Tiongkok yang menciptakan distorsi struktur pasar global.
Pemerintah Tiongkok memberikan berbagai bentuk dukungan, mulai dari subsidi energi dan bahan baku, kredit investasi dan modal kerja dengan bunga rendah, pemberian lahan industri dan dukungan infrastruktur, penanggungan biaya restrukturisasi, hingga program bail-out untuk perusahaan bermasalah, dan skema tax rebate ekspor. Karena skema kebijakan inilah, produsen baja Tiongkok mampu menjual produknya ke pasar global dengan harga yang tidak mencerminkan biaya riil—harga yang tidak dapat dilawan oleh perusahaan manapun, bahkan di negara-negara maju yang dikenal efisien dan produktif seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan.
Gelombang ekspor baja murah asal Tiongkok telah menimbulkan tekanan serius terhadap industri baja di berbagai negara dan menciptakan kerugian sistemik—termasuk yang dialami Ispat Indo. Impor baja dari Tiongkok ke Indonesia menunjukkan tren naik dalam lima tahun terakhir, dari 9,6 juta ton pada tahun 2020 menjadi 12,7 juta ton pada 2024. Pada 6 bulan pertama 2025, total impor baja Indonesia mencapai lebih dari 7,3 juta ton, dengan sekitar 3,6 juta ton berasal dari Tiongkok—setara dengan lebih dari 49 persen pangsa impor. Produk yang masuk bukan hanya slab atau billet, tetapi juga wire rod, rebar, bahkan komponen struktur baja akhir, yang secara langsung bersaing dengan produksi domestik seperti Ispat Indo.
Kondisi ini diperparah oleh kelebihan kapasitas dalam negeri. Sejak 2020, terjadi relokasi besar-besaran pabrik baja berbasis teknologi induction furnace dari Tiongkok ke negara-negara ASEAN, terutama Indonesia. Di saat yang sama, muncul pembangunan fasilitas baja terintegrasi skala besar, termasuk beroperasinya PT Dexin Steel Indonesia di Morowali dengan kapasitas 3,5 juta ton per tahun. Akumulasi ekspansi ini menciptakan tekanan signifikan terhadap pemain domestik eksisting, seperti Ispat Indo, yang tidak mendapat insentif baru dan harus bersaing dalam struktur biaya yang tidak kompetitif.
Utilisasi kapasitas Ispat Indo terus menurun dan hanya mencapai sekitar 40 persen, jauh di bawah ambang batas kelayakan profitabilitas industri berbasis scrap. Dengan beban tetap yang tinggi dan pasar yang tidak terproteksi, ruang manuver bisnis mereka semakin sempit. Mereka telah menyampaikan keluhan terhadap arus masuk produk baja dari Tiongkok sejak bertahun-tahun lalu, dan bahkan menghentikan sebagian lini produksinya pada 2019. Namun tanpa adanya kebijakan proteksi atau reformasi pasar domestik yang mendukung, tekanan tersebut terus berakumulasi hingga akhirnya berujung pada penutupan penuh pada 25 Agustus 2025.
Ketimpangan Kebijakan Global
Dalam praktik perdagangan baja global saat ini, harga murah bukan berasal dari efisiensi semata. Ia merupakan hasil dari arsitektur kebijakan negara yang dirancang secara sistematis. Hal ini terlihat nyata sebagaimana dilakukan Tiongkok selama dua dekade terakhir, yang membangun sistem industri bajanya melalui arsitektur kebijakan negara yang dirancang secara sistematis—mencakup pembiayaan murah, insentif fiskal, intervensi harga energi dan bahan baku, serta berbagai bentuk subsidi dan konsolidasi industri. Kajian “Money for Metal” (Wiley Rein LLP, 2007) mengidentifikasi setidaknya sepuluh kategori subsidi utama: pinjaman preferensial dan directed credit dari bank milik negara, injeksi ekuitas, konversi utang menjadi saham, hibah tunai, hak guna lahan di bawah harga pasar, merger yang diamanatkan pemerintah, insentif pajak dan restitusi PPN, kontrol harga energi dan bahan baku, nilai tukar yuan yang undervalued, serta pelonggaran standar lingkungan. Temuan ini diperkuat oleh laporan “Shell Game” (2024) dan “PRC Steel Industry Part 1” (2016), yang menunjukkan bahwa kebijakan subsidi dan konsolidasi terarah terus menopang ekspansi kapasitas baja baru yang tidak efisien secara komersial, namun tetap kompetitif secara harga di pasar global.
Menurut OECD, tingkat subsidi yang diterima produsen baja Tiongkok kini mencapai lima kali lipat lebih tinggi dibanding rata-rata negara mitra dagangnya. Skala subsidi ini memungkinkan ekspor baja dilakukan dengan harga sangat rendah, bahkan ketika perusahaan-perusahaan tersebut secara fundamental merugi. Hasilnya adalah banjir produk baja murah yang mengalir secara sistemik ke pasar global—bukan karena efisiensi produksi, tetapi karena struktur kebijakan yang menciptakan distorsi biaya. Situasi ini tidak mungkin dapat dilawan oleh perusahaan baja manapun, termasuk dari negara-negara maju, tanpa keterlibatan aktif dari pemerintah mereka masing-masing.
Dampaknya sangat signifikan. Ekspor baja Tiongkok melonjak dua kali lipat sejak 2020, mencapai 118 juta ton pada 2024, dan berpotensi menembus rekor baru pada 2025 setelah 77,5 juta ton diekspor hanya dalam delapan bulan pertama tahun ini—naik 10 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Arus ekspor baja murah ini tidak hanya menekan harga global, tetapi juga menggerus margin produsen di berbagai negara dan mengancam keberlangsungan industri baja nasional di banyak kawasan. Namun pada saat yang sama, banyak negara—termasuk Indonesia—tidak memiliki kapasitas fiskal, ruang regulasi industri, maupun instrumen penyeimbang struktural yang memadai untuk merespons tekanan ini secara efektif. Akibatnya, sejumlah produsen baja terpaksa menghentikan operasinya. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia—apa yang menimpa Ispat Indo sepanjang 2025 juga tercermin di berbagai belahan dunia sebagai gejala yang lebih luas.
ArcelorMittal South Africa secara resmi mengumumkan penutupan unit produksi long product di Newcastle dan Vereeniging mulai September 2025. Salah satu faktor utamanya adalah membanjirnya baja murah dari Tiongkok. Perusahaan meminta pemerintah Afrika Selatan memberikan dukungan untuk meningkatkan daya saing dan perlindungan melalui normalisasi tarif listrik industri dan memperbaiki infrastruktur logistik, serta mempercepat proteksi di perbatasan. Namun tanggapan pemerintah hanya berupa pinjaman dari Industrial Development Corporation—terlalu kecil untuk menahan tekanan struktural banjir impor murah.
Bahkan Inggris tak kebal dari gelombang ini. Dua produsen baja besar di negara itu—Tata Steel UK dan British Steel—menghadapi tekanan berat akibat membanjirnya baja murah dari Asia, terutama dari Tiongkok, yang menekan harga pasar hingga jauh di bawah biaya produksi domestik. Tekanan ini menjadi semakin berat ketika dikombinasikan dengan lonjakan biaya energi dan emisi yang tidak kompetitif. Pemerintah Inggris merespons dengan memberikan dukungan besar: Tata Steel menerima hibah £500 juta, sementara British Steel memperoleh intervensi dana sebesar £180 juta sejak April 2025 untuk menopang operasi dan mempertahankan tenaga kerja. Namun bahkan dengan bantuan tersebut, tekanan struktural akibat distorsi harga global tetap tak teratasi. Pada pertengahan 2025, British Steel memulai proses penutupan dua blast furnace di Scunthorpe.
Gelombang ekspor baja murah asal Tiongkok juga memukul keras industri baja Amerika Serikat, memicu penutupan sejumlah pabrik yang telah beroperasi selama puluhan hingga lebih dari seratus tahun. Di Ashland, Kentucky, fasilitas milik AK Steel—yang kemudian diakuisisi oleh Cleveland-Cliffs—harus ditutup permanen akibat tekanan bertubi-tubi dari baja impor yang dijual di bawah harga wajar. Di Granite City, Illinois, U.S. Steel secara bertahap menghentikan operasional blast furnace mereka, dengan alasan kelebihan kapasitas global dan ketidakmampuan bersaing dengan produk impor murah. Bahkan Columbia Steel Casting Company di Portland, Oregon—pabrik pengecoran berbasis electric arc furnace yang telah berdiri selama 121 tahun—ditutup secara permanen pada akhir 2022, menyusul tekanan berat dari persaingan offshore yang disubsidi. Kasus-kasus ini memperlihatkan bahwa tanpa perlindungan kebijakan yang memadai, bahkan produsen baja dengan sejarah panjang dan teknologi efisien pun tidak mampu bertahan dalam struktur pasar global yang timpang.
Kondisi serupa juga terjadi di berbagai negara lainnya. Menyadari ancaman sistemik dari ekspor baja murah Tiongkok, banyak pemerintah di dunia merespons dengan kebijakan proteksi yang semakin agresif untuk melindungi industri baja nasional mereka. Di Amerika Serikat, kebijakan Section 232 diperpanjang dan tarif impor baja Tiongkok dinaikkan menjadi 50 persen sejak Juni 2025—melanjutkan kebijakan yang telah diberlakukan sejak 2018. Ditambah dengan ratusan instrumen trade remedies, tarif efektif terhadap baja asal Tiongkok kini mencapai lebih dari 100 persen. Uni Eropa memperketat skema trade remedies dan mulai menerapkan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), disertai pengurangan kuota impor serta tarif tambahan bagi negara-negara dengan intensitas karbon tinggi. Kanada, Australia, India, Turki, Mesir, hingga Jepang dan Korea Selatan juga telah mengaktifkan berbagai bentuk perlindungan perdagangan—mulai dari safeguard hingga bea antidumping permanen.
Rangkaian penutupan pabrik baja di berbagai negara—dari Afrika Selatan hingga Amerika Serikat, dari Indonesia hingga Inggris—menunjukkan bahwa tekanan yang dihadapi industri baja global berpangkal pada ketimpangan struktur kebijakan. Serbuan baja murah asal Tiongkok bukan lagi sekadar isu perdagangan; ia telah menjadi ujian terhadap ketahanan industri nasional di banyak negara. Dan ketika tekanan ini tidak diimbangi dengan arsitektur kebijakan yang setara, bahkan pemain baja terbesar pun tak luput dari risiko kehancuran.
Melangkah Menuju Arah yang Lebih Berpihak
Kejadian penghentian operasi PT Ispat Indo, yang juga terjadi di negara lain, mencerminkan ketimpangan struktur kebijakan global yang menekan industri baja nasional, sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya kehadiran negara dalam menciptakan keseimbangan pasar. Dalam konteks ini, Indonesia telah mengambil berbagai langkah positif melalui pemberlakuan SNI wajib, kebijakan TKDN dalam proyek pemerintah, insentif energi melalui Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), serta perlindungan melalui instrumen pengamanan perdagangan. Semua ini adalah fondasi penting dalam memperkuat industri nasional.
Namun, tantangan yang dihadapi industri baja ke depan sangat berat dan kompleks. Tekanan global yang bersumber dari kelebihan pasokan dan distorsi harga akibat ketimpangan kebijakan—terutama dari ekspor besar-besaran Tiongkok dengan harga yang sangat murah—menuntut pendekatan kebijakan yang melampaui penguatan instrumen rutin. Dalam konteks ini, Indonesia perlu mulai mempertimbangkan kebijakan perlindungan industri sebagai bagian dari agenda strategis nasional—sebagaimana yang telah ditempuh oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa melalui pendekatan berbasis national interest dan economic security.
Langkah tersebut tidak harus dimaknai sebagai bentuk proteksionisme tertutup, melainkan sebagai bagian dari ikhtiar untuk menyeimbangkan struktur persaingan global yang sudah sangat terdistorsi. Ketika negara lain memperkuat pertahanannya secara extraordinary, Indonesia pun tidak dapat membiarkan industrinya berjalan tanpa perisai kebijakan yang setara. Karena pada akhirnya, keberlangsungan industri dasar bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kedaulatan pembangunan nasional.
Widodo Setiadharmaji adalah pendiri SMInsights dengan pengalaman lebih dari dua puluh tahun dalam bidang teknologi, strategi bisnis, dan pengembangan industri. Penulis artikel dinamika dan kebijakan industri yang dipublikasikan di Kompas, KataData, dan media nasional lainnya.