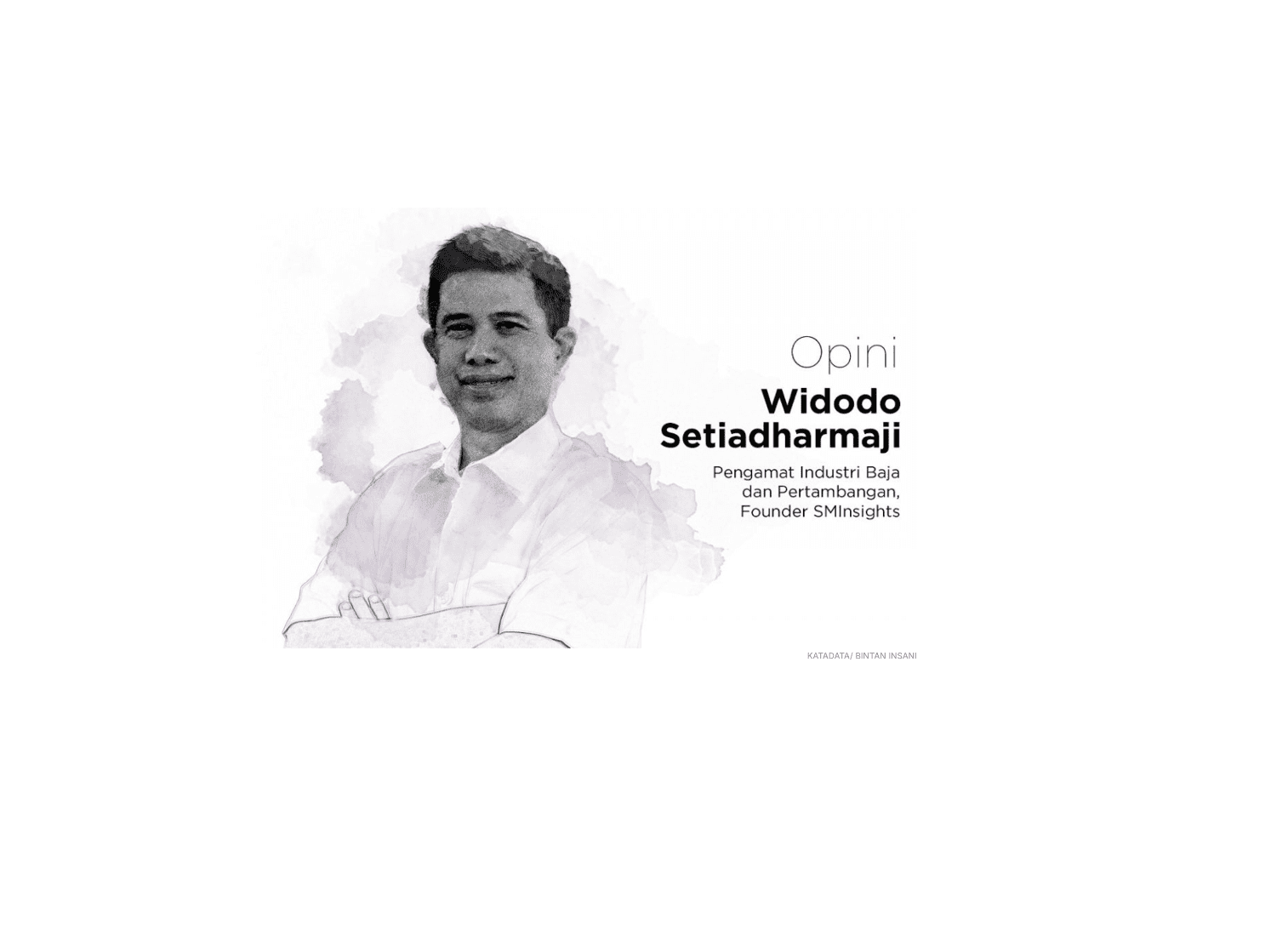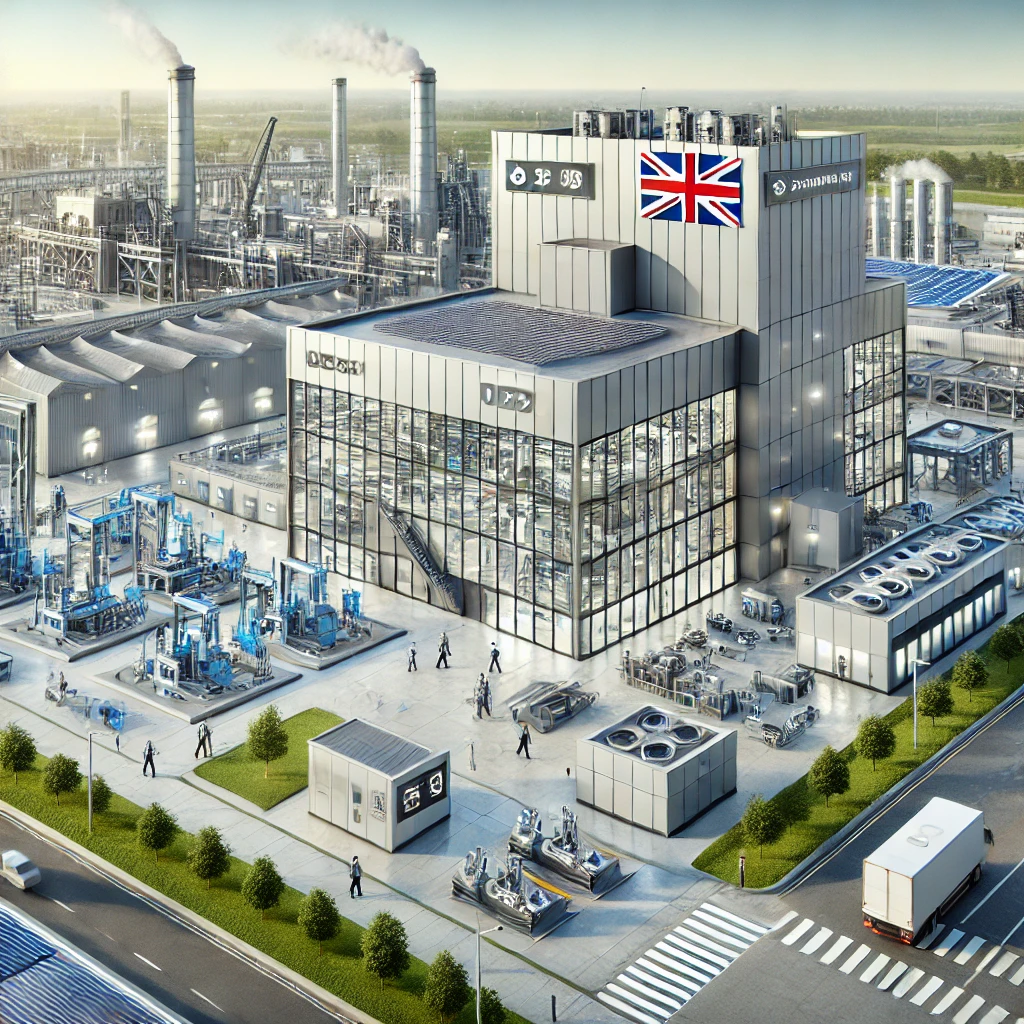Selama lebih dari satu dekade, baja Tiongkok dipersepsikan sebagai simbol daya saing global. Harga ekspornya yang rendah, volume pengiriman yang masif, serta penetrasinya ke hampir semua pasar utama dunia membentuk narasi bahwa industri baja Tiongkok adalah yang paling efisien dan paling kompetitif. Persepsi ini diterima begitu saja, bahkan kerap dijadikan tolok ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan industri baja negara lain. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, narasi tersebut menyimpan ketidaktepatan konseptual yang serius. Harga murah tidak selalu mencerminkan biaya produksi yang rendah, dan ekspor besar tidak identik dengan daya saing yang sehat.
Dominasi Tiongkok dan Ketimpangan Pasar Baja Global
Dalam lima tahun terakhir, posisi Tiongkok sebagai eksportir baja global terbesar semakin menguat dan mencapai level yang secara historis tidak tertandingi oleh negara mana pun. Berdasarkan data World Steel Association, ekspor baja Tiongkok meningkat tajam dari sekitar 53,7 juta ton pada 2020 menjadi 117,1 juta ton pada 2024, menjadikannya eksportir baja terbesar dunia dengan selisih yang sangat lebar dibandingkan negara lain. Pada 2024, volume ekspor Tiongkok tercatat hampir empat kali Jepang dan lebih dari sepuluh kali Indonesia.
Tren tersebut berlanjut pada 2025. Data resmi General Administration of Customs of China menunjukkan bahwa sepanjang Januari–November 2025, Tiongkok telah mengekspor 107,7 juta ton baja, meningkat 6,7 persen secara tahunan. Dengan volume ekspor November mencapai 9,98 juta ton, estimasi konservatif menunjukkan bahwa total ekspor baja Tiongkok sepanjang 2025 akan berada di kisaran 117,5–118 juta ton, atau setara dengan rekor tinggi tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, impor baja Tiongkok justru terus menurun, dengan total impor Januari–November hanya mencapai 5,54 juta ton. Kondisi ini menciptakan ketimpangan struktur pasar baja global yang semakin didominasi Tiongkok. Ketimpangan inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan mendasar: apakah dominasi tersebut benar-benar bersumber dari keunggulan biaya produksi, atau dari faktor struktural lain di luar efisiensi industri semata.
Meluruskan Mitos Daya Saing Tiongkok
Dominasi Tiongkok dalam industri baja global telah membentuk satu persepsi yang nyaris diterima tanpa dipertanyakan, yakni bahwa produsen baja Tiongkok pasti merupakan produsen berbiaya produksi paling rendah. Persepsi ini tampak logis pada pandangan pertama. Tiongkok adalah produsen baja terbesar dunia dengan pangsa lebih dari separuh produksi global, sekaligus eksportir baja terbesar dengan volume yang jauh melampaui negara lain. Skala produksi yang sangat besar tersebut kerap diasosiasikan secara otomatis dengan efisiensi tinggi dan struktur biaya yang unggul. Namun, asumsi tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan temuan berbagai publikasi yang membandingkan biaya produksi baja lintas negara secara sistematis.
Dalam konteks inilah laporan Selvaraju (2025) yang diterbitkan oleh Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, London School of Economics, menjadi rujukan penting. Laporan tersebut menyajikan estimasi Levelised Cost of Steel Production (LCOS) untuk berbagai negara produsen baja utama dengan metodologi yang dibakukan, sehingga memungkinkan perbandingan relatif posisi biaya produksi antar-yurisdiksi.
Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Tiongkok bukan produsen baja berbiaya terendah. Pada rute produksi BF–BOF, biaya produksi baja Tiongkok diperkirakan berada di sekitar US$545 per ton, menempatkannya pada kelompok biaya menengah secara global. Sebagai pembanding, India tercatat memiliki biaya produksi yang jauh lebih rendah, sekitar US$360 per ton, sementara Brazil berada di sekitar US$510 per ton. Yang sangat relevan bagi kepentingan Indonesia, estimasi biaya produksi BF–BOF Indonesia berada di sekitar US$475 per ton, lebih rendah dibanding Tiongkok dan relatif sebanding dengan produsen berbiaya kompetitif lainnya.
Sebaliknya, negara-negara industri maju justru berada pada tingkat biaya yang lebih tinggi. Jepang dan Korea Selatan masing-masing berada di kisaran US$600 per ton, sementara Uni Eropa (EU27) mencatat biaya produksi tertinggi dalam perbandingan ini, sekitar US$675 per ton. Jika disusun dalam satu spektrum biaya, India berada pada ujung bawah sebagai produsen berbiaya paling rendah, diikuti oleh Indonesia dan Brazil, kemudian Tiongkok di posisi menengah, dan negara-negara maju di ujung atas.
Sebagai penguat, temuan ini juga sejalan dengan berbagai publikasi independen lain. Laporan TransitionZero – Global Steel Production Costs (2022) menunjukkan bahwa pada rute produksi BF–BOF—yang merupakan jalur produksi paling dominan—biaya produksi Tiongkok berada di kelompok biaya menengah, di bawah produsen berbiaya sangat rendah seperti India dan Rusia, serta tidak lebih kompetitif dibandingkan Brazil.
Gambaran yang konsisten juga ditunjukkan dalam laporan teknis European Commission Joint Research Centre (JRC) berjudul Production Costs from the Iron and Steel Industry in the EU and Third Countries (Medarac, Moya, dan Somers, 2020). Berdasarkan pemodelan biaya pabrik baja aktual menggunakan CRU Steel Cost Model, laporan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Tiongkok memiliki keunggulan pada beberapa komponen biaya, biaya bahan baku yang relatif tinggi membuat total biaya produksi baja Tiongkok tidak berada pada tingkat terendah secara global. Dalam analisis tersebut, produsen di India, Rusia, dan sejumlah negara lain tercatat memiliki biaya produksi yang lebih rendah pada rute terintegrasi.
Berbagai rujukan di atas secara langsung menantang mitos bahwa dominasi Tiongkok dalam produksi dan ekspor baja semata-mata didorong oleh keunggulan biaya produksi. Dari perspektif biaya produksi saja, posisi Tiongkok tidak cukup kuat untuk menjelaskan tekanan harga dan penetrasi ekspor yang sangat agresif ke berbagai pasar global, sehingga penjelasan daya saing perlu dilihat melampaui faktor biaya semata.
Menata Arah Kebijakan Industri Baja 2026
Bagi Indonesia, menggugat mitos daya saing baja Tiongkok memiliki implikasi kebijakan yang sangat penting. Selama ini, tekanan dari baja impor berharga rendah kerap dijawab dengan narasi bahwa industri baja domestik kurang efisien dan harus terus menurunkan biaya. Narasi ini tidak menggambarkan kondisi persaingan yang sesungguhnya dan berpotensi mengarahkan perumusan kebijakan ke arah yang kurang tepat. Fakta bahwa banyak negara dengan industri baja yang relatif efisien tetap menerapkan trade remedies dan berbagai langkah perlindungan perdagangan terhadap baja Tiongkok menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan semata-mata efisiensi biaya produksi, melainkan ketidakseimbangan dalam struktur persaingan baja global.
Dengan memahami bahwa murahnya baja Tiongkok bukan cerminan keunggulan biaya yang murni, Indonesia dapat keluar dari jebakan diagnosis kebijakan yang keliru. Tantangan yang dihadapi bukan sekadar mengejar harga terendah, melainkan memastikan bahwa persaingan industri berlangsung di atas fondasi yang adil dan rasional. Menggugat mitos daya saing baja Tiongkok, dengan demikian, bukanlah upaya menyangkal realitas pasar, melainkan langkah awal untuk merumuskan kebijakan industri baja 2026 yang lebih tepat sasaran, berbasis pembacaan biaya yang objektif dan terverifikasi.
Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id pada 19 Januari 2026 pada tautan berikut https://katadata.co.id/indepth/opini/6966075673b00/menggugat-mitos-daya-saing-baja-tiongkok
Widodo Setiadharmaji adalah pendiri SMInsights dengan pengalaman lebih dari dua puluh tahun dalam bidang teknologi, strategi bisnis, dan pengembangan industri. Penulis artikel dinamika dan kebijakan industri yang dipublikasikan di Kompas, KataData, dan media nasional lainnya.