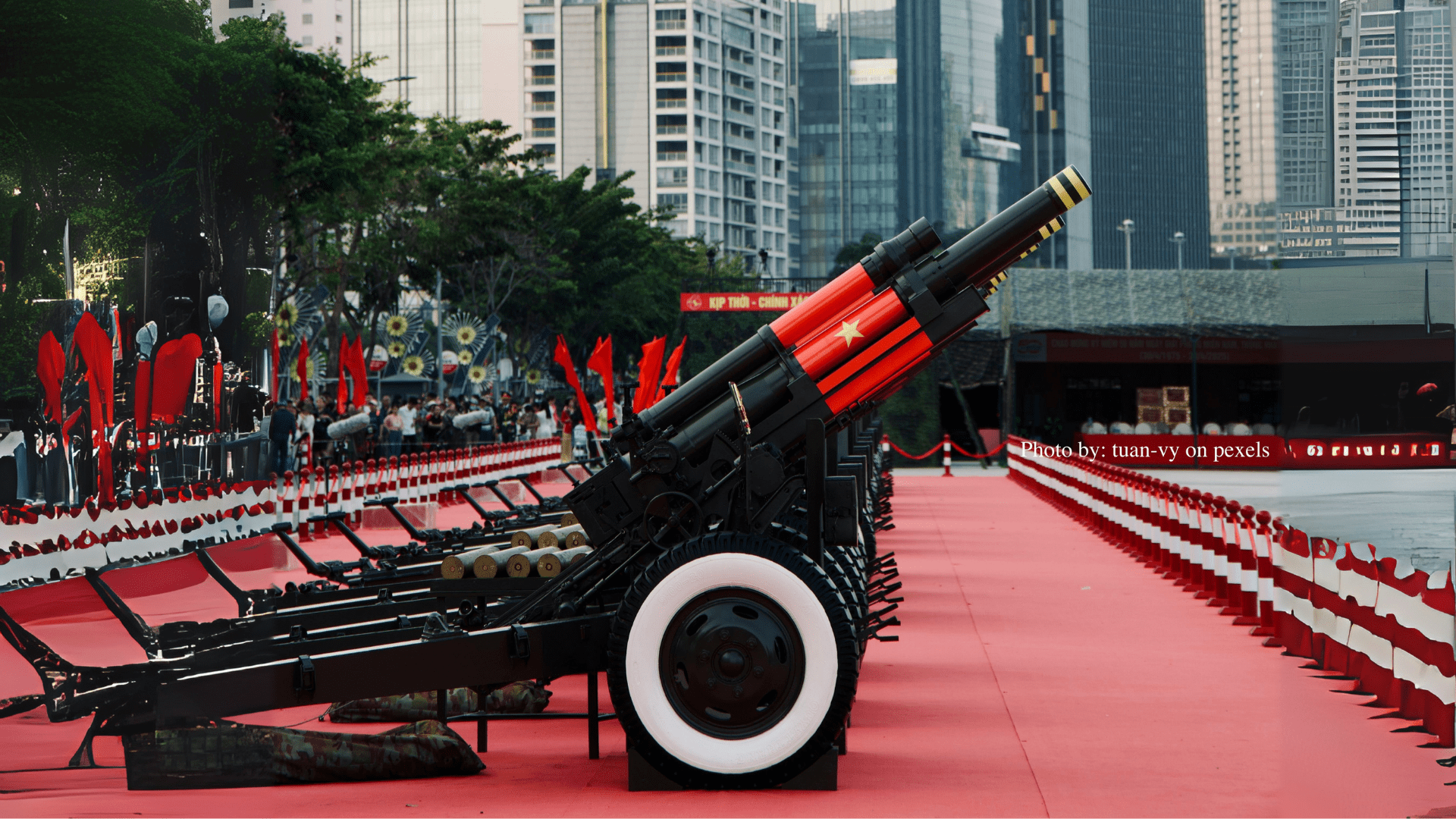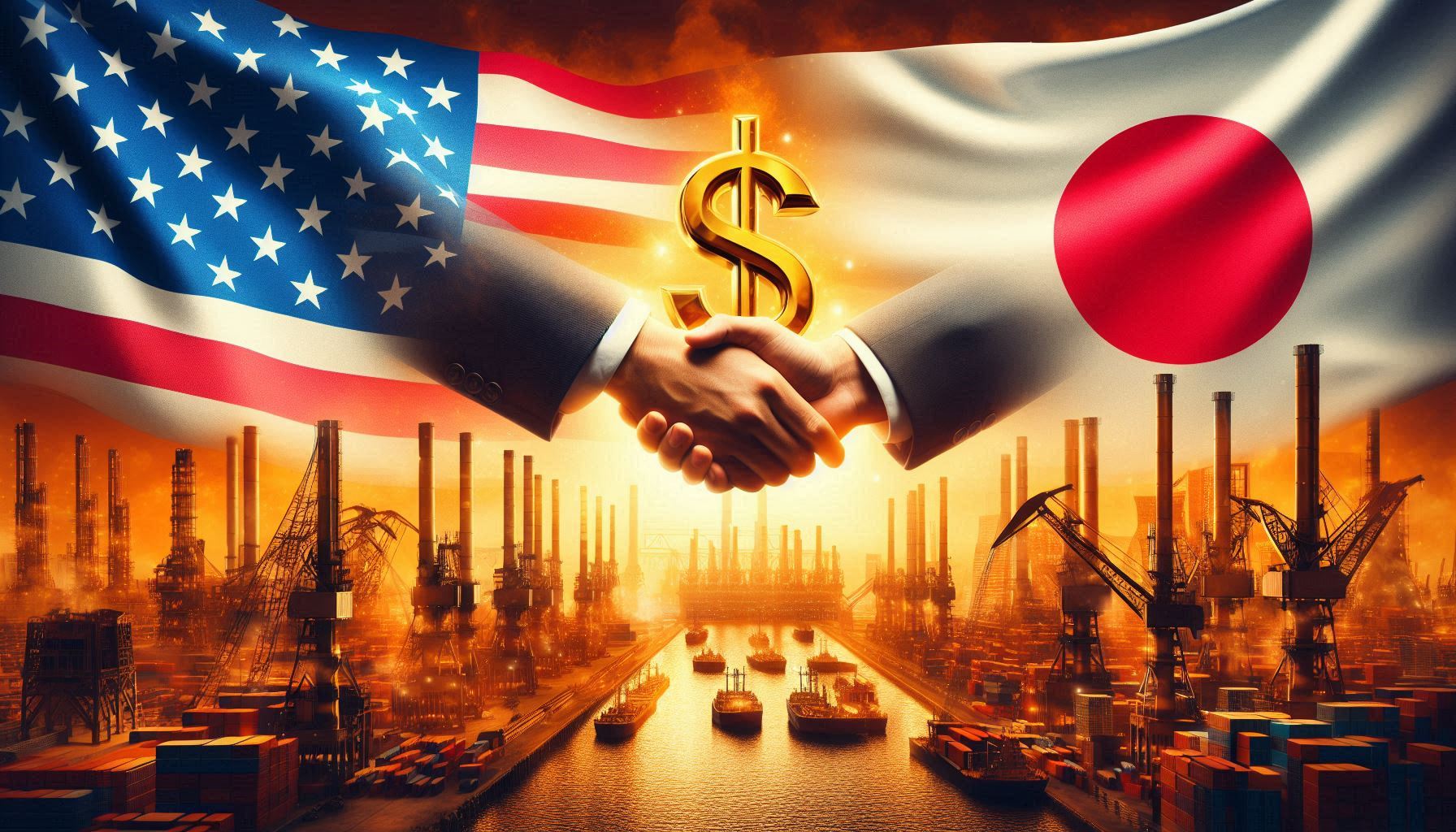Di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat perang dagang dan menguatnya proteksionisme di berbagai negara, Indonesia justru membukukan kinerja perdagangan luar negeri yang membanggakan. Pada Januari–Juni 2025, neraca perdagangan nasional mencatat surplus USD 19,48 miliar, meningkat dari USD 15,58 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Salah satu pendorong utamanya adalah ekspor besi dan baja (HS 72) senilai USD 13,79 miliar, yang menempatkannya di jajaran komoditas ekspor nonmigas terbesar bersama batubara senilai USD 11,97 miliar dan CPO senilai USD 11,43 miliar. Besi dan baja juga menjadi kontributor surplus perdagangan terbesar ketiga dengan nilai USD 9,04 miliar, setelah lemak dan minyak nabati (HS 15) serta bahan bakar mineral (HS 27).
Capaian tersebut melanjutkan tren positif tahun 2024, ketika ekspor besi dan baja mencapai USD 25,80 miliar dan impor USD 10,73 miliar, menghasilkan surplus tahunan sebesar USD 15,07 miliar. Data selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa ini bukan sekadar lonjakan sesaat, melainkan mencerminkan keberhasilan program hilirisasi yang dijalankan pemerintah. Namun di sisi lain, keluhan dari pelaku industri baja dalam negeri masih kerap terdengar, mulai dari tingginya tekanan impor hingga rendahnya tingkat utilisasi kapasitas produksi nasional. Situasi ini menciptakan sebuah paradoks: di tengah surplus perdagangan yang mengesankan, sebagian besar produsen baja nasional justru merasakan tantangan yang semakin berat dan berkelanjutan.
Dua Wajah Industri Baja Nasional
Paradoks dalam industri baja nasional berakar pada kenyataan bahwa sektor ini terbagi dalam dua segmen utama dengan fondasi dan dinamika yang sangat berbeda: stainless steel dan carbon steel. Stainless steel—yang menjadi penopang utama surplus perdagangan baja nasional—berkembang pesat berkat kebijakan hilirisasi mineral yang mendorong pemanfaatan bijih nikel domestik, pembangunan smelter terintegrasi, dan dukungan pasokan energi batubara, sehingga mampu menciptakan struktur biaya ekspor yang sangat kompetitif. Sebaliknya, carbon steel masih bergantung pada bahan baku impor seperti bijih besi, kokas metalurgi, dan scrap, dengan rantai pasok terfragmentasi dan biaya produksi yang rentan terhadap fluktuasi global.
Perbedaan struktural ini tercermin jelas dalam data perdagangan. Selama Januari–Mei 2025, ekspor stainless steel mencapai USD 10,24 miliar, dengan impor hanya USD 587 juta, menghasilkan surplus USD 9,65 miliar. Sebaliknya, carbon steel hanya mencatat ekspor USD 1,34 miliar dan impor USD 2,66 miliar, sehingga defisitnya mencapai USD 1,31 miliar. Dengan kata lain, surplus perdagangan baja nasional pada periode ini hampir sepenuhnya ditopang oleh kinerja stainless steel.
Pola serupa terjadi sepanjang 2024. Ekspor stainless steel Indonesia mencapai USD 22,27 miliar dan impor hanya USD 2,23 miliar, menciptakan surplus USD 20,04 miliar. Di sisi lain, ekspor carbon steel hanya USD 3,44 miliar, jauh di bawah impornya yang mencapai USD 5,99 miliar, menghasilkan defisit perdagangan sebesar USD 2,56 miliar. Konsistensi data ini menunjukkan bahwa keunggulan neraca perdagangan baja nasional bukanlah cerminan kekuatan seluruh sektor, melainkan dominasi tunggal oleh stainless steel.
Kesenjangan antara dua segmen ini menegaskan perlunya pendekatan kebijakan yang berbeda dan spesifik. Tidak cukup hanya mengandalkan keberhasilan stainless steel sebagai indikator kekuatan industri secara keseluruhan. Justru karena perbedaan karakter dan tantangannya, carbon steel membutuhkan perhatian khusus agar tidak terus tertinggal. Strategi pembangunan industri baja nasional ke depan harus dimulai dengan mengakui adanya ketimpangan ini secara jujur dan terbuka.
Merancang Arah Baru Industri Baja Nasional
Paradoks neraca perdagangan baja nasional—di mana surplus besar hampir seluruhnya ditopang oleh kinerja stainless steel sementara carbon steel justru mencatat defisit—menunjukkan perlunya strategi pengembangan yang tersegmentasi. Stainless steel berkembang di atas basis sumber daya domestik yang kuat, terintegrasi dalam rantai hilirisasi, dan memiliki daya saing ekspor tinggi. Carbon steel, sebaliknya, masih tertekan oleh ketergantungan impor bahan baku dan persaingan di pasar domestik. Perbedaan ini tidak dapat dijembatani dengan satu pendekatan kebijakan tunggal jika Indonesia ingin memperkuat industri baja secara menyeluruh.
Keberhasilan hilirisasi di sektor stainless steel patut diapresiasi. Larangan ekspor bijih nikel yang disertai masuknya investasi besar pada smelter telah menciptakan keunggulan ekspor, mendorong surplus neraca perdagangan, dan menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam rantai pasok global.
Di sisi lain, carbon steel menghadapi tantangan struktural yang berat. Dominasi produk impor di pasar domestik, defisit perdagangan yang terus berulang, serta rendahnya utilisasi kapasitas menunjukkan lemahnya fondasi kebijakan. Industri carbon steel rentan terhadap praktik dumping dan banjir impor, seperti yang tengah dialami banyak negara akibat kelebihan kapasitas baja global, khususnya di Tiongkok.
Penguatan industri carbon steel harus dimulai dari optimalisasi pasar domestik. Penerapan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada proyek strategis perlu diperluas agar penggunaan baja karbon lokal meningkat. Neraca komoditas baja harus difungsikan sebagai instrumen pembatas impor, hanya mengizinkan masuknya produk yang belum dapat diproduksi di dalam negeri, sehingga mencegah banjir baja murah yang merusak harga dan melemahkan produsen lokal.
Penguatan kelembagaan menjadi prioritas, termasuk pembentukan kementerian khusus baja sebagaimana India, untuk mengoordinasikan kebijakan lintas sektor secara terintegrasi. KPPI dan KADI perlu diperkuat agar respons terhadap praktik dumping dan lonjakan impor dapat dilakukan cepat, didukung sistem peringatan dini yang memantau tren harga, volume impor, dan potensi pelanggaran dagang.
Sementara itu, strategi stainless steel ke depan harus diarahkan pada peningkatan nilai tambah dan ketahanan industri. Struktur ekspor perlu bergeser ke produk hilir bernilai tinggi, mengurangi ketergantungan pada feronikel dan produk semi-finished. Diversifikasi pasar harus mengurangi konsentrasi ekspor ke Tiongkok dengan memperluas jangkauan ke ASEAN, Asia Selatan, Timur Tengah, dan wilayah baru lainnya. Pengelolaan pasokan nikel harus menjadi prioritas nasional untuk menjaga kesinambungan produksi, sementara transisi energi perlu dipercepat untuk mengantisipasi kebijakan karbon global seperti CBAM Uni Eropa.
Terlepas dari perbedaan strategi antara kedua segmen, koordinasi lintas sektor menjadi kunci. Kementerian Perindustrian, Perdagangan, ESDM, Keuangan, BKPM, dan kementerian khusus baja harus menyusun peta jalan bersama yang membedakan pendekatan untuk stainless steel dan carbon steel, namun tetap dalam kerangka penguatan ekosistem baja nasional. Dengan strategi yang tersegmentasi tetapi terintegrasi, Indonesia dapat mempertahankan keunggulan stainless steel sekaligus membangun ketahanan carbon steel. Neraca perdagangan yang kuat harus menjadi instrumen menuju kedaulatan industri baja nasional dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Artikel ini telah terbit di Opini KataData pada tautan berikut: https://katadata.co.id/indepth/opini/68a27cc325524/masalah-struktural-di-balik-kilau-kinerja-industri-baja-nasional
Widodo Setiadharmaji adalah pendiri SMInsights dengan pengalaman lebih dari dua puluh tahun dalam bidang teknologi, strategi bisnis, dan pengembangan industri. Penulis artikel dinamika dan kebijakan industri yang dipublikasikan di Kompas, KataData, dan media nasional lainnya.