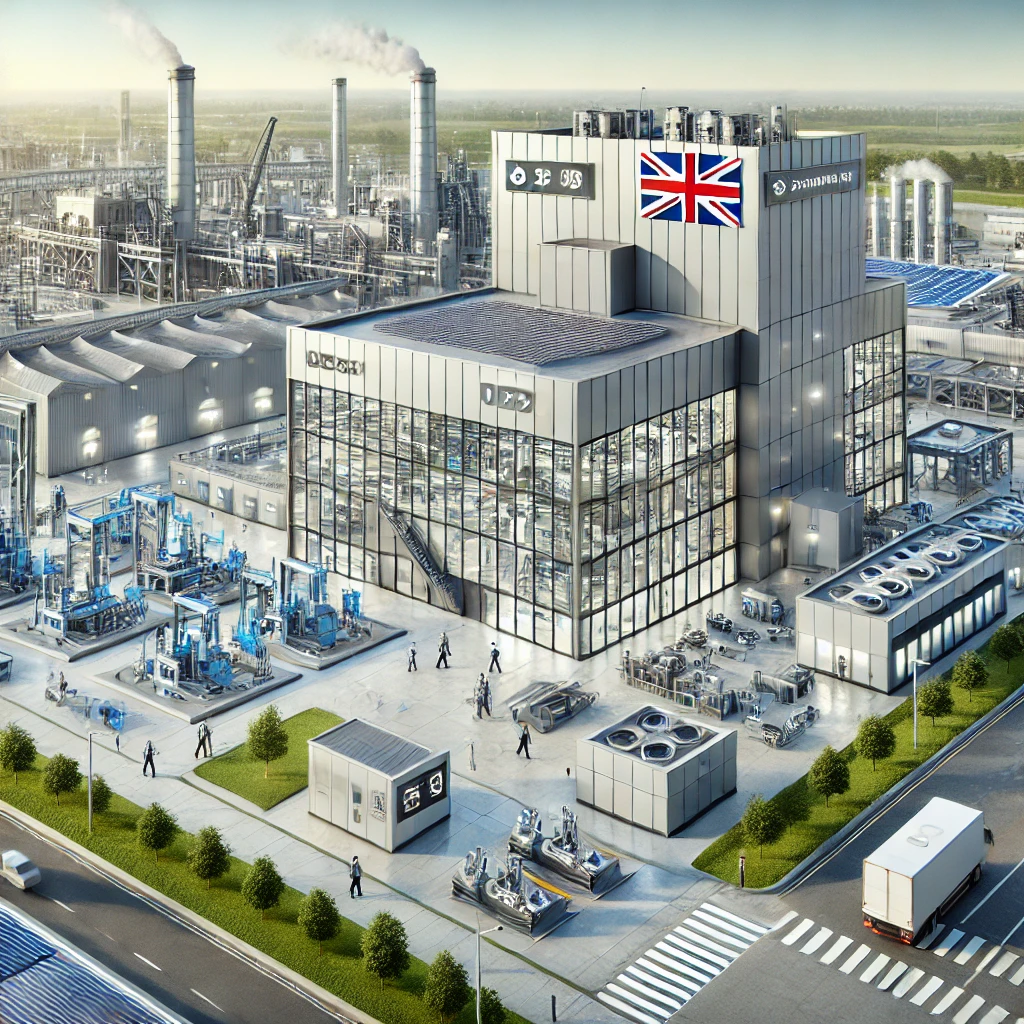Langkah Prancis menuju nasionalisasi ArcelorMittal memuncak pada malam 27 November 2025, ketika Majelis Nasional melakukan voting yang berlangsung hingga larut malam dan akhirnya menyetujui rancangan undang-undang nasionalisasi dengan 127 suara mendukung dan 41 menolak.
Usulan itu diajukan oleh La France Insoumise (LFI) — partai kiri radikal yang dipimpin Jean-Luc Mélenchon dan dikenal dengan agenda anti-korporasi serta platform ekonomi berbasis kedaulatan nasional. Dalam pandangan LFI, nasionalisasi merupakan satu-satunya cara menyelamatkan industri baja Prancis dari ancaman PHK dan deindustrialisasi.
Namun pemerintah Presiden Emmanuel Macron bersama para menteri ekonomi, industri, dan tenaga kerja justru bergerak dalam arah sebaliknya. Mereka menilai langkah tersebut bukan hanya tidak efektif, tetapi juga merupakan “ilusi proteksi” yang mengalihkan perhatian dari masalah sebenarnya: kelebihan kapasitas global, banjir impor murah dari Asia, serta ketidakseimbangan regulasi iklim dan energi di Eropa.
RUU Nasionalisasi: Dorongan Sosial-Politik yang Kuat, tetapi Jalan Legislasi Masih Panjang
RUU nasionalisasi ini lahir dari tekanan serikat pekerja dan protes berkepanjangan menyusul rencana ArcelorMittal memangkas ratusan pekerjaan di Prancis. Partai kiri radikal LFI memosisikan nasionalisasi sebagai “kemenangan strategis” untuk menyelamatkan 80.000 pekerjaan dan membangun kedaulatan industri baru berbasis transisi ekologi.
Biaya pengambilalihan diperkirakan mencapai €3 miliar, sebuah angka yang dianggap LFI “lebih kecil ketimbang biaya kehilangan kompetensi nasional”.
Meski demikian, Senat yang didominasi partai konservatif sangat mungkin menggagalkan RUU ini, sebagaimana mereka menolak proposal serupa yang diajukan Komunis pada Oktober lalu. Dengan demikian, meski kemenangan di Majelis Nasional memberi momentum politik besar, jalan menuju implementasi tetap tidak jelas.
Pemerintah: Nasionalisasi Tidak Mengatasi “Masalah Struktural” Industri Baja
Menteri Keuangan Roland Lescure secara tegas menyebut langkah nasionalisasi sebagai “jawaban populis terhadap persoalan struktural”. Dalam keterangannya, Lescure menilai bahwa penyebab tekanan utama bukanlah kepemilikan ArcelorMittal, tetapi struktur pasar global yang timpang. Ia juga mengecam “aliansi oportunis dan tidak alami antara LFI dan National Rally” yang sama-sama mendukung RUU tersebut.
Menurut Lescure, fokus Prancis seharusnya adalah strategi industri yang jelas dalam kerangka Uni Eropa—mulai dari penguatan trade defence measures hingga percepatan penerapan mekanisme penyesuaian karbon lintas batas (CBAM). Pemerintah menegaskan akan tetap menolak nasionalisasi dan bekerja pada “jawaban struktural” untuk industri baja.
Menteri Industri Sébastien Martin memperkuat pesan tersebut dengan menyebut nasionalisasi hanya menciptakan “ilusi perlindungan”. Ia menilai bahwa permasalahan utama ada pada permintaan Eropa yang melemah, biaya produksi tinggi, dan distorsi persaingan akibat masuknya impor murah dari Asia.
Impor Tiongkok Jadi Isu Sentral
Isu impor Tiongkok menjadi salah satu penyebab utama yang mengakibatkan ketimpangan yang dihadapi industri baja Eropa. Produksi baja Tiongkok telah mencapai sekitar satu miliar ton pada tahun lalu, atau lebih dari separuh produksi global. Angka ini jauh melampaui kapasitas negara-negara Eropa yang produksinya relatif kecil, seperti Jerman yang hanya berada di kisaran tiga puluh tujuh juta ton, Italia sekitar dua puluh juta ton, Spanyol sekitar dua belas juta ton, dan Prancis sekitar sebelas juta ton. Ketimpangan skala produksi yang begitu besar ini menggambarkan posisi yang sangat tidak seimbang bagi industri Eropa, terutama ketika tidak ada perlindungan memadai dari Uni Eropa terhadap arus masuk baja murah.
Menteri Tenaga Kerja Jean-Pierre Farandou menekankan bahwa persoalan inti bukanlah nasionalisasi ArcelorMittal, melainkan gelombang impor baja murah dari Tiongkok yang menekan struktur biaya produsen Eropa. Ia menilai bahwa tindakan yang diperlukan harus dilakukan di tingkat Uni Eropa melalui kebijakan perdagangan dan instrumen perlindungan pasar, bukan dengan mengambil alih aset industri secara domestik. Pernyataan ini sejalan dengan kekhawatiran yang terus disampaikan ArcelorMittal mengenai kelebihan kapasitas produksi di Asia dan persaingan yang tidak setara akibat produsen Eropa menanggung biaya karbon yang sama sekali tidak dibebankan kepada produsen baja di kawasan Asia. Seluruh dinamika ini memperkuat pandangan bahwa tekanan yang dihadapi Prancis tidak dapat dilepaskan dari struktur pasar global yang semakin didistorsi oleh selisih biaya dan kebijakan antarnegara.
ArcelorMittal: Nasionalisasi Tidak Akan Menyelamatkan Operasi Prancis
ArcelorMittal memandang bahwa perubahan kepemilikan tidak akan menghapus tantangan mendasar yang mereka hadapi. Menurut CEO Alain Le Grix de la Salle, fasilitas Prancis justru bertahan karena berada dalam jaringan ArcelorMittal global. Pabrik Dunkirk dan Fos-sur-Mer bahkan mengirim sebagian besar produk mereka ke pasar Eropa lainnya, karena permintaan domestik melemah akibat deindustrialisasi.
Perusahaan khawatir bahwa pemisahan operasi Prancis dari grup global akan memperlemah kemampuan investasi dan menempatkan pabrik-pabrik tersebut dalam posisi yang jauh lebih rawan.
ArcelorMittal juga menegaskan bahwa mereka “membayar CO₂ sementara produsen Asia tidak”, menciptakan kompetisi yang dianggap tidak adil.
Perdebatan Nasionalisasi Prancis adalah Gejala Krisis Baja Eropa dan Global
Perdebatan mengenai nasionalisasi ArcelorMittal pada dasarnya mencerminkan gejolak yang lebih luas dalam industri baja Eropa, bahkan global. Seluruh laporan dari berbagai sumber memperlihatkan pola yang sama, yakni bahwa isu ini bukan semata-mata persoalan Prancis, tetapi muncul dari kegagalan Eropa menghadapi tekanan struktural yang semakin berat. Industri baja Eropa kini berada dalam tekanan akibat kelebihan kapasitas global yang dipimpin oleh produksi Tiongkok, yang volumenya sangat besar dan terus mendorong ekspor berharga murah ke pasar internasional. Pada saat yang sama, biaya produksi di Eropa jauh lebih tinggi dibandingkan kawasan Asia maupun Amerika, terutama karena harga energi, biaya lingkungan, serta kewajiban pengurangan emisi yang tidak ditanggung produsen di wilayah lain. Eropa juga menghadapi kesulitan menerapkan agenda iklim tanpa merusak daya saing industrinya sendiri, suatu dilema yang semakin nyata ketika pabrik-pabrik baja harus membayar beban karbon yang tidak ditanggung kompetitor global.
Tekanan struktural ini sesungguhnya tidak terbatas pada Eropa. Industri baja di berbagai kawasan seperti Amerika Serikat, India, Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Timur Tengah juga menghadapi dampak dari kelebihan kapasitas global yang berpusat di Tiongkok. Negara-negara tersebut merespons dengan kombinasi safeguard, tarif antidumping, dan pembatasan impor, yang menunjukkan bahwa distorsi pasar baja kini bersifat lintas kawasan dan benar-benar global. Dengan demikian, dinamika yang memicu debat nasionalisasi di Prancis merupakan bagian dari gejolak yang lebih luas dalam tata pasar baja dunia.
RUU nasionalisasi ArcelorMittal kemudian muncul sebagai manifestasi dari keresahan sosial dan ekonomi yang berkembang di Prancis, karena banyak pihak menilai bahwa deindustrialisasi sudah memasuki tahap yang mengkhawatirkan. Namun pemerintah dan para menteri tetap menolak pendekatan tersebut, karena mereka menilai bahwa akar persoalan berada di tingkat struktural dan tidak dapat diselesaikan melalui pengambilalihan perusahaan. Menurut Pemerintah Perancis, jawaban yang paling relevan justru terletak pada arsitektur kebijakan Eropa, baik dalam perdagangan, energi, maupun mekanisme perlindungan industri, sehingga penyelesaian masalah membutuhkan koreksi kebijakan di tingkat Uni Eropa , bukan tindakan nasional di Paris.
Pembelajaran Bagi Indonesia
Kondisi yang dialami industri baja Indonesia sesungguhnya tidak berbeda dengan yang terjadi di Prancis, karena keduanya menghadapi ketimpangan struktural yang bersumber dari dukungan negara Tiongkok terhadap industrinya. Perbedaan dukungan kebijakan inilah yang menciptakan distorsi harga global dan menempatkan produsen di luar Tiongkok dalam posisi kompetitif yang rapuh. Prancis mengalami tekanan akut karena pabrik-pabrik bajanya harus bersaing dengan produk Tiongkok yang diproduksi dengan biaya energi lebih rendah berkat intervensi pemerintah yang terintegrasi, mulai dari akses pembiayaan bersubsidi, keringanan pajak, subsidi bahan baku dan energi, kemudahan logistik, dukungan ekspor, dan berbagai kebijakan negara lainnya yang secara sistematis menurunkan struktur biaya produksi. Situasi ini sangat mirip dengan apa yang dihadapi Indonesia, karena produsen baja nasional juga harus berhadapan dengan aliran impor murah yang masuk ke pasar domestik, memicu penurunan utilisasi, kompetisi harga yang tidak sehat, serta potensi ancaman terhadap kelangsungan usaha dan lapangan kerja.
Bagi Indonesia, perbedaan beban kebijakan semakin terasa karena industri baja nasional masih berkembang, skala ekonominya belum sebesar pemain global, dan beberapa segmen rantai pasok masih bergantung pada impor bahan baku atau energi yang berfluktuasi. Ketika baja Tiongkok masuk dalam jumlah besar dengan harga yang jauh di bawah biaya produksi domestik, tekanan yang tercipta bukan hanya dalam bentuk kompetisi harga, tetapi juga dalam bentuk hilangnya pasar, penurunan profitabilitas bahkan kerugian, terganggunya rencana ekspansi, dan berkurangnya ruang fiskal perusahaan untuk melakukan ekspansi dan modernisasi teknologi. Dengan sendirinya, daya saing Indonesia menjadi persoalan kebijakan negara, bukan hanya kemampuan operasional perusahaan.
Pengalaman Prancis memperlihatkan bahwa bahkan negara maju dengan teknologi tinggi dan perusahaan multinasional besar sekalipun dapat terdorong masuk ke dalam perdebatan nasionalisasi karena tekanan pasar global yang tidak seimbang. Indonesia dapat dengan mudah mengalami pola serupa apabila tidak memperkuat pengamanan perdagangan, tidak mengendalikan arus impor, atau tidak menciptakan ekosistem energi dan bahan baku yang kompetitif. Jika industri baja nasional dibiarkan menghadapi distorsi global secara sendirian, maka keberlanjutan pabrik-pabrik baja dalam negeri akan semakin rapuh dan rentan terhadap tekanan pasar yang tidak seimbang. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran negara merupakan prasyarat agar industri baja nasional tetap berdiri dan mampu bersaing di tengah dinamika pasar global yang kian tidak setara.
Widodo Setiadharmaji adalah pendiri SMInsights dengan pengalaman lebih dari dua puluh tahun dalam bidang teknologi, strategi bisnis, dan pengembangan industri. Penulis artikel dinamika dan kebijakan industri yang dipublikasikan di Kompas, KataData, dan media nasional lainnya.