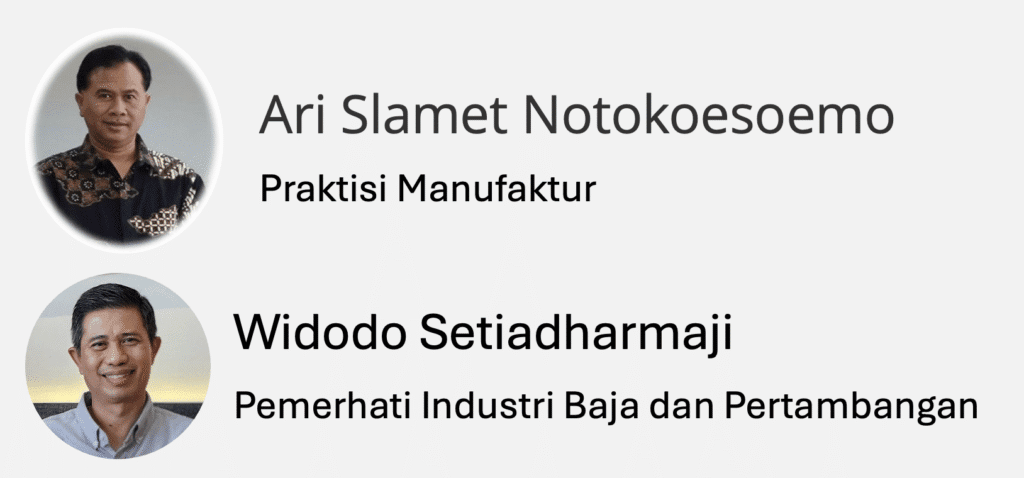
Industri baja kerap disebut sebagai mother of all industries karena perannya yang melekat pada hampir semua sektor pembangunan, mulai dari infrastruktur, transportasi, hingga pertahanan. Namun di Indonesia, industri baja justru kerap dipandang rapuh dan tertinggal. Krakatau Steel (KS), yang pernah menjadi ikon industrialisasi, kini lebih sering diberi label “pabrik tua” yang dianggap membebani negara. Kondisi ini perlu dilihat dalam perspektif yang lebih strategis dan luas. Nilai penting sebuah perusahaan tidak selalu ditentukan oleh kondisi finansial dan teknis saat ini maupun kinerja individual korporasi, melainkan oleh bagaimana ia diposisikan dalam strategi besar pembangunan nasional.
Kontroversi Garibaldi dan Relevansinya
Keputusan pemerintah Indonesia untuk mengakuisisi kapal induk bekas Giuseppe Garibaldi dari Italia menimbulkan pro-kontra. Kapal ini berusia lebih dari empat dekade dan membutuhkan biaya refit besar agar kembali layak operasi. Kritik pun muncul dari sejumlah pakar pertahanan. Beberapa pengamat mengingatkan agar pembelian Garibaldi tidak semata didorong faktor pride. Media pertahanan dari negara tetangga juga menilai langkah ini lebih bersifat simbolis ketimbang menjawab kebutuhan operasional.
Namun, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali, menegaskan tujuan dari pembelian kapal induk adalah untuk mendukung misi kemanusiaan dan penanggulangan bencana (HADR) serta patroli keamanan maritim. Pernyataan ini dapat dimaknai bahwa meskipun Garibaldi bukan kapal dengan teknologi terbaru, kehadirannya tetap memiliki arti strategis. Ia bukan sekadar alutsista tempur, melainkan dapat berfungsi sebagai simbol sekaligus instrumen nyata untuk memperkuat ekosistem maritim Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas, kehadiran kapal induk juga memberi efek psikologis dan diplomatik, menandakan kemampuan Indonesia menghadirkan proyeksi kekuatan maritim yang tidak lagi terbatas pada garis pantai, termasuk di wilayah rawan seperti Natuna yang sering menjadi sasaran praktik illegal fishing.
Dari perspektif analisis, fungsi patroli keamanan maritim inilah yang membuka implikasi ekonomi yang signifikan. Patroli berarti penegakan hukum di laut, termasuk pencegahan aktivitas ilegal seperti pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif. Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkirakan kerugian akibat praktik illegal fishing mencapai sekitar US$20 miliar per tahun. Dengan demikian, meskipun “manfaat ekonomi” tidak pernah disebutkan pemerintah sebagai tujuan akuisisi, konsekuensi strategisnya jelas: peningkatan kemampuan patroli pada akhirnya juga berarti perlindungan terhadap aset ekonomi maritim Indonesia.
Pelajaran dari Kapal Induk Tua
Kapal induk Giuseppe Garibaldi memberi pelajaran berharga tentang bagaimana sebuah aset yang tampak usang tetap bisa memainkan peran strategis. Italia sudah tidak membutuhkannya karena tidak lagi sesuai dengan standar tempur modern, tetapi Indonesia melihat relevansinya dari sisi berbeda. Garibaldi dapat diposisikan ulang sebagai platform maritim multifungsi—pangkalan helikopter, drone, dan pusat logistik untuk operasi non-perang.
Dalam konfigurasi baru, kapal induk ini bisa mengawal nelayan di Natuna, memperkuat patroli perbatasan, hingga menjadi kapal komando untuk operasi kemanusiaan di wilayah kepulauan yang terpencil. Dengan cara ini, kelemahan usia tua dan keterbatasan teknis justru berubah menjadi relevansi baru. Garibaldi bukan lagi tentang kehebatan militer, melainkan tentang kemampuan melindungi potensi ekonomi dan memberi kepastian keamanan di laut.
Pelajaran utamanya jelas: nilai sebuah aset tidak hanya ditentukan oleh spesifikasi teknisnya, tetapi oleh fungsi yang diberikan kepadanya. Keberanian pemerintah mengubah paradigma ini—dari melihat kapal induk sebagai instrumen tempur menjadi instrumen perlindungan ekonomi—menunjukkan bahwa keberanian politik dapat mengubah cara pandang terhadap aset strategis. Prinsip inilah yang kemudian bisa ditarik untuk melihat Krakatau Steel. Sama seperti kapal induk tua, KS juga dianggap rapuh dan membebani. Namun, dengan orientasi baru, ia dapat menjadi instrumen strategis pembangunan industri nasional.
Krakatau Steel: Persepsi Kapal Tua dalam Industri Baja
Krakatau Steel (KS) memiliki posisi yang unik dalam sejarah industri Indonesia. Didirikan pada era Orde Baru sebagai proyek kebanggaan nasional, KS pernah menjadi simbol ambisi industrialisasi. Dengan kapasitas produksi lebih dari 6 juta ton per tahun, pabrik di Cilegon menjadi tulang punggung industri nasional dalam penyediaan Hot Rolled Coil (HRC), Cold Rolled Coil (CRC), serta berbagai jenis baja profil, batang kawat, dan pipa untuk pasar domestik. Banyak proyek infrastruktur besar, dari jembatan hingga jalan tol, tidak lepas dari peran baja yang diproduksi KS. Nilai pasar baja domestik sendiri kini mencapai lebih dari Rp200 triliun per tahun, menjadikannya sektor strategis bagi pembangunan nasional.
Namun, seiring waktu, KS menghadapi tekanan besar. Utilisasi kapasitas kerap rendah, biaya produksi tinggi karena harga energi dan bahan baku yang mahal, serta masalah keuangan yang membuatnya sering mencatatkan kerugian. Di tengah gelombang baja impor murah dari Tiongkok, KS semakin terjepit. Bagi sebagian orang, KS tak lebih dari “pabrik tua” yang hanya menyedot subsidi dan menyumbang utang negara. Kritik ini membuat citra KS semakin rapuh di mata publik maupun investor.
Padahal, realitasnya lebih kompleks. KS juga memiliki armada modern hasil kemitraan dengan raksasa global. Krakatau Posco, hasil kerja sama dengan Posco Korea Selatan, mengoperasikan salah satu fasilitas produksi Pelat dan HRC paling modern di Asia Tenggara. Sementara itu, Krakatau Nippon Steel Indonesia (KNSI) menghasilkan baja otomotif berkelas dunia untuk pabrikan mobil di dalam dan luar negeri. Kehadiran aset-aset modern ini ibarat kapal pengiring yang tangguh, memperkuat posisi kapal induk KS dalam mengawal ekosistem industri baja nasional. Namun kinerjanya hingga kini belum sepenuhnya meyakinkan, sehingga persepsi KS sebagai kapal tua masih kuat melekat di mata publik.
Nilai sejati KS, sebagaimana Garibaldi, bukan ditentukan oleh kondisinya hari ini, melainkan oleh potensinya. Tanpa KS, industri hilir seperti otomotif, konstruksi, manufaktur energi, hingga pertahanan akan kehilangan jangkar pasokan baja. Impor memang bisa menutup celah, tetapi artinya ketergantungan nasional semakin dalam. KS tetap satu-satunya pemain domestik dengan skala cukup besar untuk menjadi tulang punggung ekosistem baja nasional. Yang diperlukan bukan sekadar mempertahankan apa adanya, melainkan mendefinisikan ulang peran dan orientasinya.
Nilai strategis KS kian jelas bila dikaitkan dengan visi Indonesia Emas 2045. Kebutuhan baja nasional diproyeksikan melampaui 100 juta ton per tahun—target yang mungkin saja tercapai melalui arus investasi asing, tetapi peran nasional dalam industri strategisnya akan sulit diwujudkan tanpa kehadiran KS. Sulit membayangkan Indonesia mampu membangun kemandirian industri apabila sebagian besar kapasitas baja nasional justru dimiliki dan dikendalikan asing.
Menjadikan KS sebagai Kapal Induk Ekonomi
Bagaimana menjadikan KS sebagai “Giuseppe Garibaldi” industri baja nasional? Kuncinya ada pada keberanian mengambil langkah reposisi besar. Seperti Garibaldi yang diposisikan ulang, KS pun harus berubah dari produsen baja umum menjadi kapal induk industri baja nasional.
Langkah pertama adalah konsolidasi. Saat ini, industri baja nasional berjalan sendiri-sendiri. Ada pemain yang lebih memilih mengimpor baja murah untuk keuntungan jangka pendek, ada yang berfokus pada hilirisasi nikel, dan ada pula yang sekadar bertahan dengan kapasitas terbatas. Fragmentasi ini melemahkan kekuatan kolektif. KS harus menjadi pusat gravitasi, pengendali rantai pasok, dan penjaga keseimbangan pasar. Dalam posisi ini, KS bukan pesaing, melainkan “mother vessel” yang memastikan seluruh ekosistem tetap hidup.
Langkah kedua adalah redefinisi fungsi. KS harus berhenti berfokus semata pada produk HRC dan CRC yang mudah dipukul oleh impor murah. Sebaliknya, ia harus bergerak ke produk strategis: baja untuk energi hijau, transportasi massal, pertahanan, dan infrastruktur premium. Dengan produk bernilai tambah, KS bisa keluar dari perang harga yang merugikan. Seperti Garibaldi yang kini menjadi kapal patroli besar, KS pun harus menjadi penyedia baja strategis untuk proyek-proyek yang menentukan masa depan bangsa.
Langkah ketiga adalah modernisasi. Sama seperti Garibaldi yang direfit agar bisa mengoperasikan drone dan helikopter, KS harus masuk ke era digitalisasi dan efisiensi energi. Investasi pada teknologi baru, diversifikasi produk, dan sistem produksi cerdas adalah syarat mutlak. Proses ini memang mahal, tetapi tanpa modernisasi, KS akan tetap menjadi kapal tua yang lamban dan rapuh. Dengan modernisasi, KS bisa kembali relevan, tidak hanya untuk pasar domestik tetapi juga sebagai pemain di pasar regional.
Manfaat Strategis bagi Pembangunan Nasional
Reposisi KS sebagai kapal induk industri baja nasional akan membawa dampak langsung terhadap pembangunan. Pertama, kepastian pasokan baja domestik akan mengurangi ketergantungan pada impor. Pada 2024, nilai impor baja Indonesia mencapai sekitar US$10,7 miliar, sementara ekspor mencapai US$25,8 miliar. Meski surplus perdagangan terjaga, dominasi impor di segmen tertentu masih menjadi ancaman serius bagi industri dalam negeri. Dengan KS yang kuat, celah ini bisa ditekan.
Kedua, KS yang stabil akan menopang hilirisasi mineral. Proyek besar seperti smelter nikel, pabrik baterai, hingga transisi energi ke energi terbarukan membutuhkan baja dalam jumlah besar. Tanpa suplai domestik, proyek-proyek tersebut bergantung pada harga global yang fluktuatif. KS dapat menjadi jaminan ketersediaan material untuk proyek strategis nasional.
Ketiga, industri baja yang terkonsolidasi akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan industri turunan. Konsumsi baja per kapita Indonesia masih sekitar 70–80 kilogram, jauh tertinggal dibanding Tiongkok di atas 600 kilogram, Jepang di atas 400 kilogram, dan Korea Selatan di atas 900 kilogram. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan pasar domestik masih terbuka sangat lebar, seiring dengan urbanisasi, industrialisasi, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Proyeksi kebutuhan baja Indonesia pada tahun 2045 diperkirakan akan melampaui 100 juta ton per tahun. Dalam konteks itu, peran KS menjadi krusial, bukan hanya sebagai produsen baja, tetapi sebagai motor penggerak yang memastikan akselerasi konsumsi baja berjalan sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan visi Indonesia Emas 2045.
Dampak ekonominya pun luar biasa. Studi Oxford Economics (2019) menunjukkan bahwa setiap 1 dolar AS yang diinvestasikan di industri baja akan menghasilkan multiplier effect sebesar 2,5 dolar AS di rantai pasok dan 13 dolar AS di industri terkait. Begitu pula setiap 1 pekerjaan di industri baja dapat memunculkan 6,5 pekerjaan tambahan di rantai pasok dan 35 pekerjaan di sektor terkait. Artinya, memperkuat KS bukan hanya soal kapasitas produksi, melainkan juga soal menciptakan efek berantai yang mampu menggerakkan perekonomian nasional secara luas.
Tantangan dan Risiko Revitalisasi
Namun, transformasi ini tidak mudah. Biaya restrukturisasi KS akan besar. Modernisasi teknologi, digitalisasi, dan diversifikasi produk memerlukan investasi ratusan hingga miliaran dolar. Tanpa dukungan kebijakan fiskal dan pembiayaan yang kuat, upaya ini bisa tersendat.
Selain itu, resistensi internal tidak terhindarkan. Banyak pelaku industri yang diuntungkan oleh arus impor murah akan menolak konsolidasi. Sebagian anggota asosiasi baja bahkan memegang izin impor, sehingga konflik kepentingan sering kali muncul. Jika pemerintah tidak tegas menata tata niaga, upaya menjadikan KS kapal induk bisa digagalkan oleh kepentingan jangka pendek.
Penguatan dan sinkronisasi kebijakan tetap menjadi tantangan utama bagi industri baja nasional. Dalam tatanan perdagangan baja yang terdistorsi dan sarat campur tangan negara, perlindungan pasar domestik secara menyeluruh menjadi keharusan: pencegahan praktik dumping, penindakan non-circumvention yang mengakali tarif, penegakan SNI untuk menutup ruang produk non-standar, serta pengawasan atas berbagai praktik perdagangan curang lain yang merugikan industri nasional. Tanpa perlindungan yang konsisten dan komprehensif, industri baja domestik akan terus digempur produk impor murah. Namun, perlindungan saja tidak cukup. Dari sisi energi, skema HGBT sebenarnya memberi peluang besar untuk menekan biaya produksi, tetapi implementasinya masih jauh dari optimal sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan. Industri baja juga membutuhkan dukungan kebijakan modernisasi teknologi, insentif investasi, akses modal kerja yang kompetitif, serta ekosistem riset dan inovasi agar mampu menghasilkan baja bernilai tambah tinggi. Lebih jauh lagi, integrasi dengan hilirisasi mineral dan sektor manufaktur harus diperkuat, sementara diplomasi perdagangan perlu ditingkatkan, bukan hanya untuk menjaga akses pasar ekspor, tetapi juga untuk melindungi pasar domestik dari praktik perdagangan yang tidak adil. Semua ini menegaskan bahwa menjadikan KS sebagai kapal induk bukan hanya tugas korporasi, melainkan juga tanggung jawab negara.
Belajar dari Keberanian Garibaldi
Keputusan membeli Garibaldi mengajarkan bahwa langkah strategis tidak selalu populer. Membeli kapal induk tua mungkin tampak aneh, tetapi dengan reposisi fungsi, keputusan itu berpotensi menghasilkan manfaat strategis yang melampaui sekadar aspek militer. Pelajaran yang sama berlaku bagi Krakatau Steel.
KS sering dipersepsikan sebagai kapal tua yang rapuh, tetapi dengan keberanian untuk mereposisi peran, ia justru dapat tampil sebagai kapal induk industri nasional. Melalui konsolidasi, redefinisi, dan modernisasi, KS bisa keluar dari bayang-bayang beban masa lalu dan berubah menjadi instrumen strategis pembangunan. Sama seperti Garibaldi yang diposisikan ulang untuk melindungi laut, KS harus diposisikan ulang untuk melindungi dan memperkuat ekosistem industri nasional.
Kini saatnya Indonesia melihat KS bukan semata sebagai pabrik baja yang menghitung untung-rugi, melainkan sebagai kapal induk pembangunan industri nasional. Keberanian politik yang sama seperti pada Garibaldi diperlukan: bukan untuk mengelola aset semata, tetapi untuk membangun ekosistem yang lebih kokoh demi masa depan.
Disclaimer: Tulisan ini disusun terbatas pada perspektif bagaimana kapal induk Giuseppe Garibaldi bisa dimaknai sebagai instrumen perlindungan kawasan dan kekayaan nasional Indonesia. Fokusnya bukan pada kajian kelayakan operasional maupun doktrin pertahanan, melainkan sebagai analogi konseptual untuk menegaskan nilai strategis suatu aset dan menarik pelajaran bagi pembangunan industri baja nasional.
Widodo Setiadharmaji adalah pendiri SMInsights dengan pengalaman lebih dari dua puluh tahun dalam bidang teknologi, strategi bisnis, dan pengembangan industri. Penulis artikel dinamika dan kebijakan industri yang dipublikasikan di Kompas, KataData, dan media nasional lainnya.



