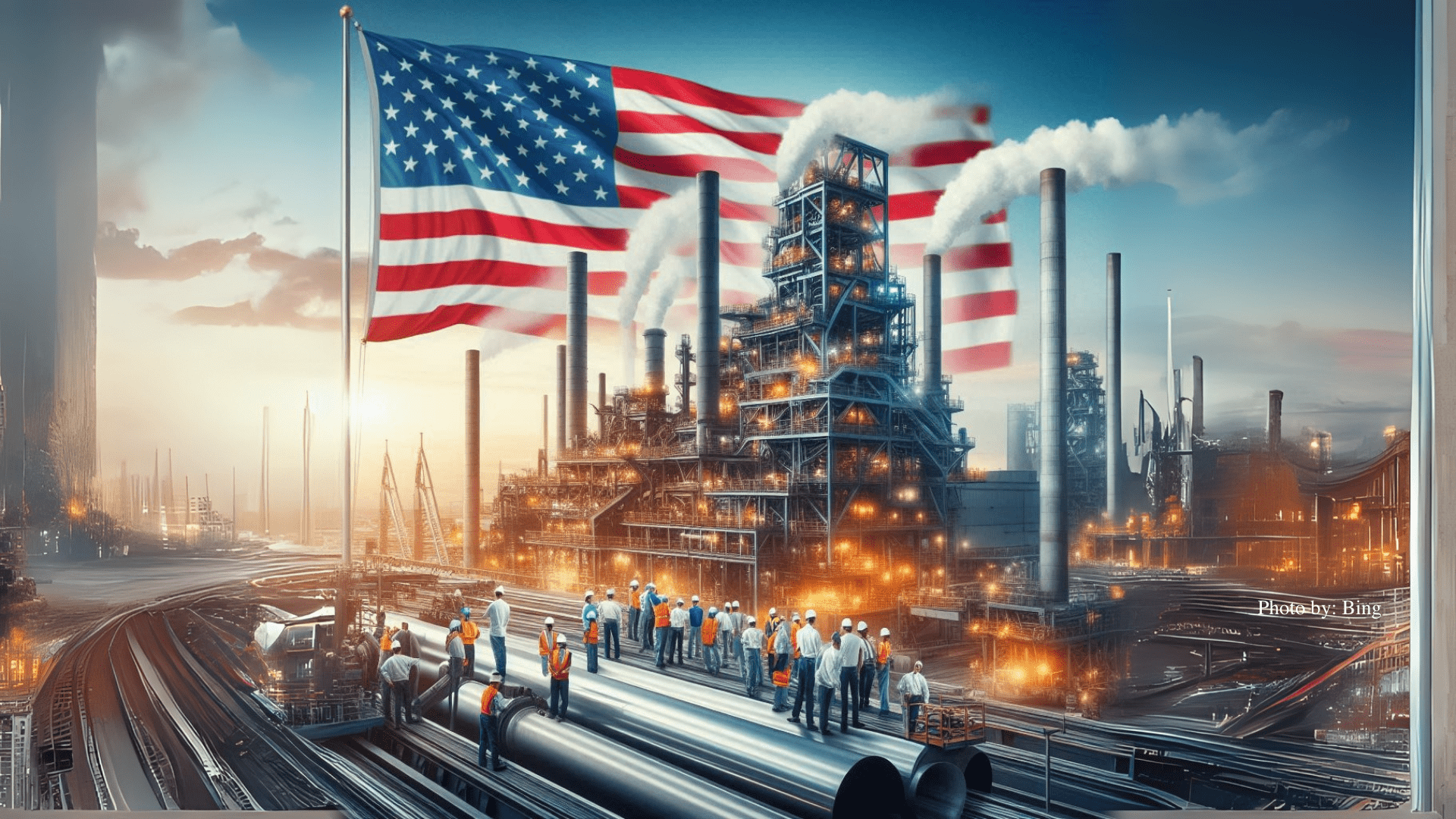Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) merupakan instrumen strategis pemerintah untuk menekan ongkos energi industri baja, terutama pada lini produksi yang paling intensif menggunakan energi. Dengan tarif gas sebesar US$7/MMBtu dan listrik industri yang relatif murah, HGBT menempatkan Indonesia di kuartil biaya energi rendah global, dengan posisi yang kompetitif terhadap Amerika Serikat yang menikmati energi murah. Keunggulan biaya ini membuka ruang ekspor ke pasar premium seperti AS dan Uni Eropa, namun keunggulan tersebut sangat bergantung pada konsistensi implementasi HGBT. Tanpa pelaksanaan yang penuh dan menyeluruh, keunggulan biaya ini hanya akan menjadi potensi di atas kertas.
Namun, daya saing industri baja tidak ditentukan oleh harga gas semata. Pengalaman global menunjukkan bahwa energi murah hanyalah fondasi; tanpa proteksi pasar, dukungan fiskal, dan kebijakan industri yang menyeluruh, penurunan biaya energi tidak akan cukup untuk menjaga keberlangsungan industri baja nasional.
Energi sebagai Komponen Biaya Utama Industri Baja
Struktur biaya produksi baja, baik melalui rute blast furnace–basic oxygen furnace (BF–BOF) maupun electric arc furnace (EAF), menunjukkan bahwa bahan baku dan energi adalah komponen dominan. Pada rute BF–BOF, porsi bahan baku bisa mencapai 55–75 persen dari total ongkos produksi, jauh lebih tinggi dibanding rute EAF yang hanya 35–60 persen. Hal ini dapat dipahami karena proses BF–BOF sangat bergantung pada bijih besi dan kokas yang harganya berfluktuasi di pasar global, sedangkan EAF lebih fleksibel karena menggunakan scrap atau DRI sebagai bahan utama.
Energi menempati posisi kedua terbesar. Pada BF–BOF, kontribusinya 10–25 persen, terutama dalam bentuk panas dari gas, kokas, dan bahan bakar tambahan untuk mendukung reduksi bijih besi di blast furnace. Sementara pada EAF, energi menyumbang 15–25 persen karena proses peleburan sangat bergantung pada listrik dan gas. Artinya, jika BF–BOF lebih sensitif terhadap harga kokas dan bijih besi, maka EAF lebih rentan terhadap fluktuasi tarif listrik.
Komponen lain relatif lebih kecil, meskipun tetap signifikan. Biaya tenaga kerja langsung berkisar 4–8 persen pada kedua rute, sedangkan biaya perawatan menambah sekitar 3–7 persen. Overhead pabrik dan selling, general & administrative (SGA) mengisi 5–10 persen, relatif seragam di semua rute. Depresiasi bervariasi antara 5–12 persen untuk BF–BOF dan 5–10 persen untuk EAF, sangat dipengaruhi oleh umur pabrik dan intensitas modal yang ditanamkan.
Dari struktur ini terlihat bahwa daya saing biaya baja nasional terutama dipengaruhi oleh dua faktor utama: ketersediaan bahan baku dan harga energi. Pada rute BF–BOF, biaya sangat ditentukan oleh akses terhadap bijih besi dan kokas, sementara pada rute EAF faktor penentu adalah harga scrap atau DRI. Indonesia menghadapi tantangan karena tidak memiliki cadangan bijih besi, kokas, maupun scrap yang memadai. Dalam kondisi ini, instrumen kebijakan seperti HGBT menjadi sangat penting, karena energi merupakan satu-satunya komponen besar dalam struktur biaya yang masih dapat dikendalikan dari dalam negeri untuk menopang daya saing industri baja nasional.
| Komponen biaya | BF–BOF (rentang tipikal) | EAF–Scrap (rentang tipikal) | Keterangan |
| Bahan baku utama | 55–75% | 35–60% | BF–BOF tinggi karena bijih + kokas; EAF tergantung scrap/DRI |
| Energi (listrik, gas, bahan bakar) | 10–25% | 15–25% | EAF sangat intensif listrik; BF–BOF lebih banyak panas dari kokas/gas |
| Tenaga kerja langsung | 4–8% | 4–8% | Relatif serupa di kedua rute, tergantung produktivitas |
| Perawatan | 3–7% | 3–7% | Biaya pemeliharaan rutin peralatan dan fasilitas |
| Overhead pabrik & SGA | 5–10% | 5–10% | Termasuk administrasi, manajemen, utilitas umum |
| Depresiasi | 5–12% | 5–10% | Dipengaruhi umur aset dan intensitas investasi modal |
Sumber: Informasi publik dari berbagai sumber daring per 28 September 2025.
Kebutuhan Energi Spesifik dalam Proses Produksi Baja
Industri baja merupakan salah satu sektor paling intensif energi di dunia. Setiap tahapan proses, mulai dari reduksi bijih besi hingga rolling dan coating, membutuhkan konsumsi energi spesifik dalam jumlah besar yang secara langsung membentuk struktur biaya produksi. Karena itu, memahami perbandingan antara kebutuhan energi teoritis, benchmark global, dan standar nasional Indonesia menjadi penting untuk menilai daya saing energi industri baja.
Sebagai titik awal, para peneliti seperti Fruehan dan tim dari Carnegie Mellon University telah menghitung theoretical minimum energy requirement, yakni kebutuhan energi paling rendah secara termodinamika. Perhitungan ini menunjukkan batas ideal, misalnya proses blast furnace ironmaking memerlukan sekitar 9,8 GJ/t untuk mengubah bijih besi menjadi besi cair dengan menggunakan kokas, coke oven gas, pulverized coal, serta listrik. Namun angka tersebut hanya bersifat teoritis. Dalam praktiknya, konsumsi selalu lebih tinggi karena adanya kehilangan panas, yield loss, dan keterbatasan teknologi. Proses lanjutan seperti steelmaking, rolling, dan coating pun tetap membutuhkan energi tambahan yang besar karena berlangsung pada temperatur tinggi.
Untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan, digunakan benchmark global yang disusun dari berbagai sumber seperti kajian DOE/Fruehan, IEA, dokumen BAT Uni Eropa, data asosiasi industri (worldsteel, JISF), serta laporan teknis perusahaan baja besar. Benchmark ini mencerminkan konsumsi energi aktual di pabrik modern yang efisien. Secara konsisten, nilainya lebih tinggi dibanding batas teoritis karena adanya heat losses dan kebutuhan energi tambahan untuk menjaga stabilitas operasi. Sebagai contoh, pada proses hot strip rolling, benchmark global menunjukkan kebutuhan energi panas sebesar 2,0–2,4 GJ/t ditambah 120–180 kWh/t listrik, setara 2,4–3,0 GJ/t— jauh di atas batas teoritis 0,03 GJ/t.
Indonesia pun telah menetapkan Standar Industri Hijau (SIH) untuk industri baja yang menentukan batas konsumsi energi spesifik di setiap tahapan proses. Angka-angka SIH ini menempatkan konsumsi energi nasional masih dalam rentang benchmark global. Misalnya, hot strip mill di Indonesia dibatasi pada 2,55 GJ/t panas dan 155 kWh/t listrik, relatif sebanding dengan benchmark global 2,0–2,4 GJ/t panas dan 120–180 kWh/t listrik. Hal serupa terlihat pada cold rolling maupun coating, yang menunjukkan bahwa efisiensi teknis pabrik baja dalam negeri tidak tertinggal jauh dari praktik terbaik dunia. Dengan kata lain, posisi efisiensi proses Indonesia sudah berada dalam spektrum praktik baik; yang paling menentukan selanjutnya adalah harga gas dan listrik.
Dari perbandingan ini, dapat ditarik tiga kesimpulan utama. Pertama, industri baja memang padat energi sehingga harga energi menjadi faktor penentu utama biaya produksi. Kedua, benchmark global merepresentasikan kinerja aktual terbaik yang dapat dicapai teknologi saat ini, bukan angka teoritis. Ketiga, posisi Indonesia melalui SIH berada dalam rentang benchmark global meskipun belum sepenuhnya menyamai level terbaik, sehingga daya saing energi nasional lebih ditentukan oleh harga gas dan listrik daripada efisiensi proses.
Tabel. Kebutuhan Energi Spesifik Proses Produksi Baja
(Theoretical Minimum vs Benchmark Global vs Indonesia – SIH)
| Proses | Theoretical Minimum (GJ/t) | Benchmark Global (GJ/t + kWh/t) | Indonesia – SIH (GJ/t + kWh/t) |
| BF ironmaking | 9,8 | 14–20 GJ/t panas | 9,25 GJ/t panas; 121 kWh/t listrik |
| BOF steelmaking | 0,3 | 0,5–1,0 GJ/t panas | 0,52 GJ/t panas; 66 kWh/t listrik |
| EAF steelmaking | 1,5 | 2,0–3,5 GJ/t panas | 2,50 GJ/t panas; 420–550 kWh/t listrik |
| Hot strip rolling | 0,03 | 2,0–2,4 GJ/t panas + 120–180 kWh/t listrik | 2,55 GJ/t panas; 155 kWh/t listrik |
| Cold rolling | 0,02 | 1,0–1,4 GJ/t panas + 200–330 kWh/t listrik | 0,96–1,28 GJ/t panas; 130–147 kWh/t listrik |
| Coating – konstruksi | — | 3–5 GJ/t panas + 40–100 kWh/t listrik | 3,51–4,35 GJ/t panas; 50–110 kWh/t listrik |
| Coating – warna | — | 5–8 GJ/t panas | 6,13–7,32 GJ/t panas |
| Pipa ERW | — | 0,5–0,9 GJ/t panas + 40–80 kWh/t listrik | 0,62–0,72 GJ/t panas; 45–65 kWh/t listrik |
Sumber: Informasi publik dari berbagai sumber daring per 28 September 2025.
Posisi Indonesia di Tengah Disparitas Harga Energi Global
Daya saing biaya energi industri baja ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu konsumsi spesifik dan harga energi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana posisi harga energi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara produsen utama baja dunia. Perbandingan ini akan memperlihatkan kontras yang tajam: ada negara dengan energi sangat murah seperti Amerika Serikat, ada pula kawasan dengan biaya energi paling tinggi seperti Uni Eropa, sementara negara-negara Asia menempati posisi menengah dengan karakteristik masing-masing.
Amerika Serikat menikmati keunggulan gas murah berkat revolusi shale yang membuat pasokan domestik berlimpah. Harga Henry Hub pada September 2025 hanya sekitar US$3,2/MMBtu, sementara tarif listrik industri rata-rata mencapai US¢17/kWh. Kombinasi ini menempatkan AS sebagai salah satu produsen baja dengan biaya energi terendah di dunia, meskipun tarif listriknya jauh lebih tinggi daripada di Indonesia.
Sebaliknya, Uni Eropa menghadapi harga energi tertinggi akibat ketergantungan pada impor LNG dan gas pipa, terutama sejak pasokan Rusia terganggu pascaperang Ukraina. Harga gas di TTF Belanda tercatat sekitar US$11,1/MMBtu pada akhir Agustus 2025, sedangkan tarif listrik industri menembus US¢30/kWh. Ditambah beban pajak karbon dan pungutan energi terbarukan, biaya energi industri baja Eropa menjadi yang paling tidak kompetitif di dunia.
Tiongkok berada di posisi menengah. Tarif listrik industri relatif terkendali di sekitar US$0,099/kWh berkat proteksi negara, namun harga gas berbasis LNG Asia Timur masih cukup tinggi, sekitar US$10/MMBtu pada pertengahan 2025. Posisi ini membuat biaya energi Tiongkok tetap lebih besar daripada Indonesia dengan HGBT, meskipun masih lebih rendah dibanding Jepang dan Korea Selatan.
India menunjukkan perkembangan berbeda. Reformasi kebijakan energi membuat harga gas domestiknya pada September 2025 dipatok sekitar US$6,99/MMBtu, lebih rendah dari Jepang dan Korea Selatan. Dengan tarif listrik industri sekitar US$0,13/kWh, biaya energi India berada di bawah Jepang dan Korea Selatan, tetapi tetap lebih tinggi daripada AS maupun Indonesia dengan HGBT.
Jepang dan Korea Selatan masih sangat rentan karena hampir seluruh kebutuhan energi mereka dipenuhi impor LNG. Di Jepang, harga LNG impor rata-rata mencapai US$11,5/MMBtu dengan tarif listrik industri sekitar US¢22,7/kWh, sementara di Korea Selatan harga gas sekitar US$11,3/MMBtu dan listrik US¢12,2/kWh. Kombinasi ini membuat industri baja di kedua negara menanggung beban energi yang sangat tinggi.
Meski menanggung biaya energi yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain, produsen baja Jepang dan Korea Selatan tetap mampu mempertahankan daya saing global. Strategi yang mereka jalankan bukan sekadar menekan biaya, melainkan mengalihkan fokus produksi ke segmen bernilai tambah tinggi seperti baja otomotif, baja perkapalan, serta baja khusus untuk industri migas dan konstruksi berat. Daya saing ini diperkuat dengan pola kemitraan erat bersama sektor hilir, di mana produsen baja berperan tidak hanya sebagai pemasok material, tetapi juga mitra dalam riset, desain, dan inovasi. Dengan pendekatan ini, tingginya ongkos energi tidak langsung melemahkan posisi mereka, karena spesialisasi produk dan nilai tambah yang tinggi memungkinkan ruang margin lebih besar sekaligus menciptakan keterikatan jangka panjang dengan industri pengguna.
Indonesia menempati posisi berbeda berkat kebijakan HGBT. Harga gas untuk industri baja ditetapkan US$7/MMBtu, jauh lebih rendah daripada Jepang, Korea Selatan, maupun Tiongkok. Sementara itu, tarif listrik industri hanya sekitar US¢7/kWh berkat subsidi silang dan bauran energi fosil domestik. Kombinasi gas dan listrik murah ini menempatkan Indonesia di kuartil biaya rendah global dan kompetitif terhadap Amerika Serikat; Indonesia diuntungkan oleh listrik yang lebih murah, sementara AS diuntungkan oleh gas yang lebih murah.
| Wilayah | Harga Gas (US$/MMBtu) | Harga Listrik (US$/kWh) |
| Amerika Serikat | ~3,2 | ~0,1747 |
| Uni Eropa | ~11,1 | ~0,30 |
| Tiongkok | ~10,0 | ~0,099 |
| India | ~6,99 | ~0,13 |
| Jepang | ~11,5 | ~0,227 |
| Korea Selatan | ~11,3 | ~0,122 |
| Indonesia (HGBT) | 7,0 | ~0,07 |
Sumber: Informasi publik dari berbagai sumber daring per 28 September 2025.
Biaya Energi Baja Indonesia: Simulasi dengan dan tanpa HGBT
Untuk menilai dampak HGBT secara nyata terhadap daya saing biaya, harga energi di tiap wilayah diterjemahkan ke dalam bentuk biaya energi produksi baja. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan asumsi konsumsi panas dan listrik pada setiap lini proses sesuai dengan benchmark global dan Standar Industri Hijau (SIH) yang ditetapkan Kementerian Perindustrian. Dalam simulasi ini, negara maju diasumsikan beroperasi dengan konsumsi spesifik terbaik, India berada di titik tengah antara konsumsi terbaik dan median, sedangkan Indonesia menggunakan konsumsi spesifik batas atas sebagaimana tercantum dalam SIH.
Biaya energi per produk dihitung dengan menjumlahkan kebutuhan energi dari setiap tahapan dalam skema pabrik baja terintegrasi. Untuk HRC berbasis BF–BOF, misalnya, biaya mencakup BF ironmaking, BOF steelmaking, dan hot strip mill. Pada CRC ditambahkan proses cold rolling, sementara pada baja lapis ditambahkan galvanizing atau coating. Dengan pendekatan ini, konsumsi energi dianggap seragam sesuai standar SIH, sehingga perbedaan biaya antarwilayah sepenuhnya mencerminkan disparitas harga gas dan listrik.
Total Biaya Energi (Gas + Listrik) per Produk (US$/t)
| Wilayah | HRC BF–BOF | CRC BF–BOF | Coated Konstruksi | Coated Warna | Pipa ERW |
| AS | 58 | 96 | 112 | 118 | 67 |
| UE | 116 | 186 | 230 | 251 | 133 |
| Tiongkok | 56 | 85 | 118 | 136 | 64 |
| India | 71 | 96 | 146 | 158 | 83 |
| Jepang | 122 | 167 | 233 | 249 | 143 |
| Korea Selatan | 85 | 116 | 172 | 196 | 100 |
| Indonesia (HGBT) | 51 | 69 | 104 | 119 | 60 |
| Indonesia (tanpa HGBT) | 82 | 96 | 146 | 166 | 83 |
Tabel di atas memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh kombinasi harga gas dan listrik terhadap biaya energi baja di setiap wilayah. Dengan skema HGBT, Indonesia konsisten berada pada spektrum biaya terendah secara global dan, dalam skenario perbandingan ini, dapat tampil lebih rendah daripada AS untuk beberapa produk utama. Tren serupa terlihat pada baja lapis dan pipa ERW, dengan biaya energi Indonesia (US$104–119/t untuk coated, US$60/t untuk ERW) lebih rendah daripada pesaing regional maupun Uni Eropa, serta kompetitif terhadap AS.
Namun, posisi ini berubah drastis bila HGBT dicabut. Dengan harga gas kembali ke level US$11–12/MMBtu, biaya energi melonjak 30–60 persen tergantung produk. Untuk HRC, biayanya naik dari US$51/t menjadi US$82/t, lebih mahal daripada AS (US$58/t), Tiongkok (US$56/t), dan India (US$71/t). Pada produk hilir, lonjakan ini bahkan lebih besar sehingga menempatkan biaya energi baja Indonesia di atas AS, Tiongkok, dan India.
Konsekuensi dari perubahan posisi ini sangat serius. Dengan HGBT, Indonesia berada di kuartil biaya rendah global, mampu menghadapi serbuan impor Tiongkok di pasar domestik sekaligus memiliki ruang menembus pasar ekspor premium seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa sepanjang memenuhi ketentuan bea masuk, trade remedies, dan standar emisi dan persyaratan lainnya. Sebaliknya, tanpa HGBT, keunggulan tersebut hilang. Biaya energi Indonesia lebih tinggi dari AS dan India, sementara Tiongkok kembali lebih murah. Dalam kondisi itu, industri baja nasional akan kehilangan daya saing di pasar ekspor sekaligus semakin rentan terhadap banjir impor baja murah di dalam negeri, khususnya dari Tiongkok.
Karena itu, HGBT bukan sekadar instrumen subsidi energi, melainkan instrumen vital untuk menjaga daya saing industri baja nasional. Ia menentukan apakah Indonesia bisa berada di kelompok produsen berbiaya rendah bersama AS dan Tiongkok, atau justru jatuh ke kelompok biaya menengah bersama India. Apalagi, industri baja nasional masih bergantung pada bahan baku impor, baik bijih besi maupun batubara kokas. Dalam situasi seperti ini, HGBT menjadi alat domestik yang paling nyata untuk menopang daya saing. Tanpanya, produsen dalam negeri akan sangat sulit menemukan sumber keunggulan lain.
Realitas HGBT: Masalah Implementasi di Lapangan
Meskipun perhitungan biaya energi menunjukkan posisi Indonesia sangat kompetitif dengan HGBT, kenyataannya implementasi di lapangan jauh lebih kompleks. Pertama, adanya pembatasan kuota membuat industri tidak selalu memperoleh pasokan gas dengan harga HGBT. Alokasi biasanya dihitung harian atau bulanan, dan ketika kuota habis, industri terpaksa membeli sisa kebutuhan dengan harga pasar non-HGBT yang jauh lebih tinggi. Data Kemenperind pada beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan realisai kuota ini menyusut: tahun 2022 sekitar 63–94% dari kontrak di Jawa BagianTimur ; tahun 2023 kuota HGBT tinggal sekitar 86% dari kontrak di Jawa Bagian Barat; tahun 2024 turun menjadi ±60% di Jawa Bagian Barat; bahkan pada 2025 hingga Agustus, kontrak di Riau, Kepulauan Riau, dan Jawa Bagian Barat hanya sekitar 48% yang terpenuhi dengan HGBT.
Kedua, harga gas bumi yang benar-benar dibayarkan industri pada akhirnya berada di atas HGBT. Ketidakseimbangan antara kuota HGBT yang ditetapkan pemerintah dan ketersediaan pasokan hulu membuat perusahaan tidak pernah menikmati harga US$6–7/MMBtu untuk seluruh kebutuhannya. Harga riil menjadi rata-rata tertimbang antara volume ber-HGBT dan volume di luar kuota yang dibayar dengan harga pasar, sehingga biaya energi aktual lebih tinggi daripada hasil simulasi.
Ketiga, ketika kuota HGBT habis, fallback yang ditawarkan adalah LNG regasifikasi dengan harga jauh lebih mahal. Penawaran harga LNG regas PGN berada di kisaran US$16,7–16,9/MMBtu (sekitar 2,5× HGBT). Dengan proporsi non-HGBT yang membesar, banyak perusahaan terpaksa membeli pada level ini, sehingga keunggulan biaya yang terlihat pada tabel pada praktiknya belum sepenuhnya terwujud. Seluruh permasalahan tersebut membuat potensi daya saing yang seharusnya lahir dari kebijakan HGBT tidak terealisasi secara optimal. Akibatnya, keunggulan biaya industri baja dalam negeri belum benar-benar terbangun, sementara arus impor tetap bertahan pada tingkat yang relatif tinggi
Saat HGBT Tak Lagi Mampu Membendung Baja Murah Impor
Pengalaman global menunjukkan bahwa harga energi yang kompetitif saja tidak cukup untuk menjamin keberlanjutan industri baja. Amerika Serikat adalah contoh yang paling jelas. Meski menikmati harga gas yang sangat murah berkat revolusi shale gas, produsen baja domestik tetap kesulitan bersaing di pasar domestik karena banjir baja impor dengan harga sangat rendah, khususnya dari Tiongkok. Dalam kondisi ini, keunggulan biaya energi tidak mampu menahan tekanan harga dari produk impor.
Itulah sebabnya pemerintah AS menambahkan lapisan proteksi perdagangan yang sangat kuat. Section 232 diberlakukan untuk mengenakan tarif tambahan 50 persen pada baja impor, sementara ratusan perkara antidumping (AD) dan antisubsidi (CVD) menghasilkan tarif efektif yang dalam banyak kasus mencapai ratusan persen untuk produk tertentu. Perisai ganda inilah yang memastikan produsen baja domestik tetap bisa beroperasi, sekalipun biaya energi mereka sudah sangat rendah.
Hal serupa juga ditempuh negara-negara Teluk. Meskipun mereka memiliki akses gas alam berbiaya murah—misalnya di Arab Saudi harga gas industri bisa di bawah US$2/MMBtu—proteksi perdagangan tetap dipakai untuk menjaga daya saing domestik. Pada 2019, GCC menerapkan safeguard terhadap flat-rolled steel menyusul lonjakan impor HRC/CRC; pada 2016–2017 ada penyelidikan AD untuk rebar dan wire rod dari Tiongkok, Turki, dan India; serta perkara galvanis/coated pada 2020–2021 di UEA. Semua ini membuktikan bahwa harga energi murah hanyalah fondasi, tetapi tanpa proteksi pasar yang tegas, industri tetap bisa terhimpit oleh kompetisi global yang tidak seimbang.
Dalam konteks Indonesia, HGBT adalah instrumen strategis yang menempatkan industri baja nasional di kuartil biaya energi terendah di Asia jika diterapkan dengan volume sesuai kebutuhan tiap perusahaan dan dengan harga sesuai ketetapan HGBT. Dengan skema penuh seperti ini, biaya energi Indonesia lebih murah dibandingkan Tiongkok, India, maupun Jepang, sehingga memberikan fondasi daya saing yang kuat. Namun, keunggulan ini hanya berlaku dalam skenario ideal.
Pada kenyataannya, implementasi HGBT masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari pembatasan kuota, harga riil yang dibayar industri di atas ketentuan, hingga fallback ke LNG regasifikasi yang jauh lebih mahal. Seluruh hambatan ini membuat potensi daya saing yang seharusnya lahir dari kebijakan HGBT tidak terealisasi secara optimal, sehingga industri dalam negeri belum sepenuhnya menikmati biaya energi rendah dan impor tetap bertahan pada tingkat yang relatif tinggi.
Terlebih lagi, jika HGBT dicabut sepenuhnya, biaya energi Indonesia justru akan lebih tinggi daripada Tiongkok, India, dan bahkan Amerika Serikat. Dalam skenario tersebut, posisi daya saing energi nasional akan runtuh, membuat industri baja semakin rentan terhadap serbuan impor, khususnya dari Tiongkok, sekaligus kehilangan peluang menembus pasar ekspor premium seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Karena itu, HGBT saja tidak cukup. Ia harus menjadi bagian dari paket kebijakan yang lebih luas, sebagaimana ditunjukkan oleh Amerika Serikat yang tidak hanya menurunkan biaya energi tetapi juga memperkuat industrinya melalui tarif impor, preferensi domestik, serta dukungan fiskal. Di Indonesia, penurunan biaya energi perlu diiringi dengan pengamanan pasar melalui instrumen perdagangan yang tegas, penerapan TKDN yang konsisten agar belanja negara menyerap baja dalam negeri, pemberlakuan SNI wajib untuk menjamin standar kualitas, serta pengawasan barang impor agar tidak ada celah bagi praktik curang yang merugikan produsen domestik. Dukungan pemerintah juga harus mencakup insentif fiskal dan pembiayaan yang mendorong investasi teknologi rendah emisi sehingga industri baja nasional tidak tertinggal dalam transisi global.
Dengan kombinasi kebijakan seperti inilah momentum penurunan biaya energi bisa benar-benar ditransmisikan menjadi peningkatan utilisasi pabrik, pengurangan kesenjangan biaya dengan pesaing, serta penguatan posisi Indonesia baik di pasar domestik maupun di pasar ekspor. TTanpa langkah-langkah komplementer tersebut, HGBT hanya akan menjadi kebijakan setengah jalan dalam membentengi industri baja dari derasnya banjir impor baja murah. Hampir semua negara kini telah memperkuat proteksi dan dukungan terhadap industri bajanya masing-masing, sehingga sudah saatnya Indonesia mengambil langkah serupa agar industri baja nasional mampu bertahan, tumbuh, dan berkembang sebagai pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Disclaimer: Harga energi dan tarif listrik yang digunakan mengacu informasi publik dari berbagai sumber daring per 28 September 2025. Perbandingan biaya dilakukan dengan asumsi konsumsi spesifik sesuai benchmark global dan Standar Industri Hijau (SIH) dari Kementerian Perindustrian. Data ini bersifat indikatif dan sebaiknya diuji kembali terhadap sumber resmi terbaru apabila akan dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Widodo Setiadharmaji adalah pendiri SMInsights dengan pengalaman lebih dari dua puluh tahun dalam bidang teknologi, strategi bisnis, dan pengembangan industri. Penulis artikel dinamika dan kebijakan industri yang dipublikasikan di Kompas, KataData, dan media nasional lainnya.