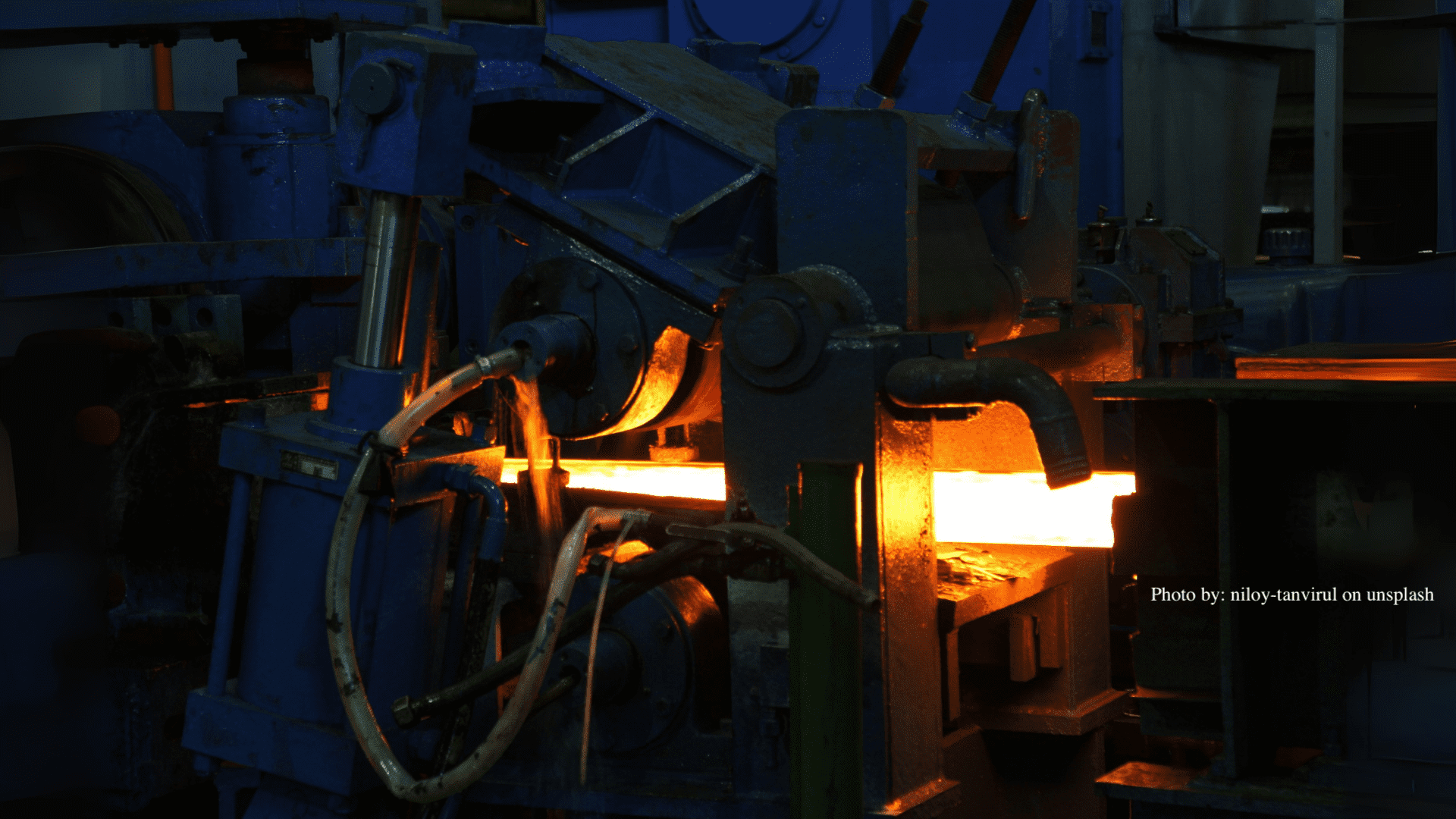Kesepakatan dagang Indonesia–Amerika Serikat yang diumumkan melalui Joint Statement on Framework for United States–Indonesia Agreement on Reciprocal Trade pada 17 Juni 2025, menandai babak baru dalam hubungan perdagangan kedua negara. Secara umum, kesepakatan ini bertujuan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Serikat melalui penurunan tarif pada berbagai komoditas. Pemerintah Indonesia menyambut baik langkah ini sebagai peluang strategis untuk mendorong ekspor nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Namun dari perspektif industri baja, terdapat sejumlah ketentuan yang perlu dicermati secara lebih kritis. Pertama, kesepakatan ini tidak menghapus tarif baja sebesar 50% yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap seluruh negara, termasuk Indonesia, di bawah Executive Order 14105. Bahkan, tarif tersebut diperkuat dengan penerapan berbagai trade remedies seperti antidumping, countervailing duties, dan safeguard yang masih terus berlaku. Dengan demikian, tidak terdapat relaksasi kebijakan tarif bagi baja Indonesia dalam kesepakatan ini. Kedua, terdapat satu klausul penting yang justru membawa konsekuensi strategis jangka panjang: Indonesia secara eksplisit berkomitmen untuk bergabung dengan Global Forum on Steel Excess Capacity (GFSEC) dan mengambil tindakan efektif dalam mengatasi kelebihan kapasitas global di sektor baja. Ini merupakan pertama kalinya Indonesia secara terbuka menyatakan komitmen tersebut di dalam dokumen resmi bilateral dengan Amerika Serikat.
Di sinilah letak dilema yang dihadapi Indonesia. Di satu sisi, keikutsertaan dalam GFSEC dapat memperkuat posisi diplomatik Indonesia dan membuka peluang untuk ikut merumuskan tata kelola kapasitas baja global, sekaligus memenuhi persyaratan diplomatik dari mitra strategis seperti Amerika Serikat. Namun di sisi lain, Indonesia saat ini telah dan sedang melaksanakan program hilirisasi— khususnya dalam pengolahan nikel menjadi stainless steel — yang telah secara signifikan meningkatkan kapasitas produksi dan menjadikan Indonesia salah satu eksportir stainless steel terbesar dunia. Lebih jauh lagi, Indonesia tengah merancang agenda ekspansi kapasitas industri baja hingga 100 juta ton pada 2045 guna mendukung visi Indonesia Emas.
GFSEC sendiri didirikan dengan misi utama untuk menekan ekspansi kapasitas baja global, melalui transparansi, pelaporan pembangunan kapasitas baru, pengawasan subsidi, dan mekanisme tekanan kolektif terhadap negara-negara yang dianggap memperparah overcapacity. Dalam konteks ini, partisipasi Indonesia dalam forum tersebut berpotensi menjadi bumerang — jika ekspansi kapasitas domestik tidak dapat dijustifikasi sebagai kebutuhan dalam negeri, maka Indonesia bisa diposisikan sebagai kontributor baru dalam krisis kelebihan kapasitas global.
Lebih jauh lagi, komitmen terhadap GFSEC dapat menjadi instrumen pengawasan terhadap kebijakan hilirisasi nasional. Insentif fiskal, keterlibatan BUMN, dan proyek strategis lain dapat dipersepsikan sebagai bentuk subsidies with distortive effect, sehingga memicu tekanan internasional. Jika tidak diantisipasi dengan baik, hal ini dapat membatasi fleksibilitas Indonesia dalam mengatur arah industrialisasi baja nasional.
Dengan demikian, dilema Indonesia sangat jelas: bagaimana memanfaatkan peluang dari kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat, tanpa terperangkap dalam komitmen multilateral yang justru dapat membatasi ruang gerak ekspansi kapasitas baja nasional — sebuah agenda yang sangat penting untuk menopang ambisi pembangunan ekonomi jangka panjang Indonesia.
Sejarah dan Tujuan Pembentukan GFSEC
Global Forum on Steel Excess Capacity (GFSEC) dibentuk atas prakarsa negara-negara G20 pada 2016 sebagai platform untuk menangani krisis kelebihan kapasitas baja global[1]. Forum ini resmi didirikan pada Desember 2016 di Berlin, dengan anggota mencakup negara-negara G20 dan anggota OECD yang tertarik, mewakili ~90% produksi dan kapasitas baja dunia. Tujuan GFSEC adalah mendorong transparansi data, kerja sama kebijakan, dan aksi kolektif untuk mengurangi kapasitas berlebih yang menekan harga baja, mendistorsi perdagangan, dan mengancam stabilitas industri baja secara global. GFSEC beroperasi melalui pertemuan rutin tingkat pejabat dan tahunan tingkat menteri, melibatkan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan industri baja dari 28 ekonomi penghasil baja terbesar. Seluruh anggota berdiri setara dan diharapkan mematuhi Prinsip Berlin yang disepakati pada 2017, termasuk komitmen untuk tidak memberikan subsidi atau dukungan pemerintah yang mendistorsi pasar dan mendorong penyesuaian kapasitas secara market-based.
Sejak berdiri, GFSEC telah menghasilkan beberapa kemajuan. Melalui tekanan politik dan pertukaran informasi, surplus kapasitas baja global sempat menurun dari puncaknya ~793 juta ton pada 2015 menjadi sekitar 526 juta ton pada 2019 saat semua negara G20 (termasuk Tiongkok) terlibat aktif[6]. Tiongkok, produsen baja terbesar dunia, melaporkan telah memangkas kapasitas lebih dari 150 juta ton selama 2016–2018 sebagai bagian dari upaya bersama tersebut[9]. Namun, masalah over capacity belum tuntas. Setelah 2019, kelebihan kapasitas kembali meningkat seiring bertambahnya kapasitas baru di berbagai negara sementara pertumbuhan permintaan lesu. Saat ini kelebihan kapasitas diproyeksikan mencapai 630–721 juta ton dalam beberapa tahun ke depan sehingga beberapa negara menganggap peran GFSEC kembali krusial.
Forum ini secara kelembagaan dikelola oleh OECD, namun tidak bersifat mengikat secara hukum. Keanggotaannya bersifat sukarela, dan kebijakan yang disepakati tidak memiliki sanksi formal, melainkan mengandalkan pengawasan kolektif (peer pressure) dan ekspektasi politik. Meski demikian, rekomendasi GFSEC telah berulang kali dijadikan dasar tindakan dagang oleh negara-negara anggotanya, terutama Uni Eropa dan Amerika Serikat, dalam menerapkan trade remedies terhadap negara yang dianggap memperburuk overcapacity global.
Keterlibatan Indonesia dan Posisi Negara Produsen Baja Utama
Indonesia pertama kali bergabung dengan GFSEC pada tahun 2016 sebagai salah satu negara G20. Keterlibatan ini berlangsung aktif pada fase awal, terutama hingga tahun 2018, dengan partisipasi delegasi Indonesia dalam pertemuan tingkat tinggi dan komitmen pelaporan kapasitas nasional. Namun sejak 2019, Indonesia tercatat tidak lagi menghadiri beberapa pertemuan resmi GFSEC dan absen dalam laporan kolektif OECD, hingga akhirnya tidak lagi terdaftar dalam keanggotaan aktif per 2021.
Ketiadaan Indonesia dalam GFSEC selama beberapa tahun terakhir tampaknya dipengaruhi oleh orientasi kebijakan hilirisasi nasional, yang bertumpu pada ekspansi kapasitas stainless steel melalui peningkatan investasi di sektor smelter dan downstream. Dalam konteks ini, ketentuan GFSEC yang menekankan pada pengendalian ekspansi kapasitas dan pembatasan dukungan kebijakan pemerintah dapat dinilai tidak selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional.
Namun, melalui kesepakatan dagang terbaru dengan Amerika Serikat, Indonesia menyatakan komitmen untuk bergabung kembali dalam GFSEC dan mengambil langkah konkret sesuai prinsip-prinsip forum tersebut. Ini menandai perubahan besar dalam posisi Indonesia dan menimbulkan pertanyaan strategis atas arah kebijakan industri baja nasional ke depan.
Sikap berbagai negara terhadap GFSEC sangat bervariasi. Tiongkok, sebagai pemicu utama overcapacity global, sempat bergabung sejak awal pembentukan GFSEC namun menarik diri secara resmi pada 2020. Pemerintah China menilai bahwa GFSEC terlalu bias terhadap mereka dan cenderung digunakan sebagai instrumen tekanan politik dan dagang. China menolak tudingan sebagai satu-satunya sumber overcapacity dan menekankan bahwa pengawasan kapasitas harus dilakukan secara adil, tidak diskriminatif, dan mengakui hak negara berkembang untuk membangun industrinya.
India juga menolak untuk bergabung, dengan alasan serupa. Sebagai negara berkembang dengan kebutuhan ekspansi infrastruktur dan industrialisasi, India menilai bahwa keanggotaannya dalam GFSEC dapat membatasi fleksibilitas kebijakan industrinya. India lebih memilih untuk mempertahankan kebijakan protektif dan subsidi domestik tanpa komitmen multilateral yang bisa mengekang kapasitasnya.
Korea Selatan dan Jepang memilih tetap berada dalam GFSEC namun dengan sikap kritis. Korea Selatan menekankan pentingnya kesetaraan dalam penerapan prinsip forum dan menolak generalisasi bahwa semua ekspansi kapasitas adalah ancaman. Jepang, meskipun pendukung kuat GFSEC, tetap menjalankan kebijakan ekspansi di sektor high-end steel dan mempertahankan subsidi R&D melalui skema inovasi industri.
Uni Eropa merupakan pendukung paling aktif dari GFSEC dan menjadikan forum ini sebagai landasan legitimasi untuk berbagai kebijakan dagang defensif. Melalui kerangka GFSEC, Uni Eropa mendorong penegakan prinsip transparansi, pengendalian kapasitas, dan pelaporan subsidi—yang kemudian dijadikan dasar dalam penerapan berbagai tindakan trade remedies, terutama terhadap China. Uni Eropa secara aktif mendorong agar negara-negara berkembang tunduk pada standar transparansi dan pelaporan kapasitas serta subsidi.
Tantangan Strategis dalam Bayang-Bayang Komitmen GFSEC
Keterlibatan kembali Indonesia dalam GFSEC menimbulkan sejumlah tantangan strategis yang harus dipetakan dengan cermat. Pertama, target kapasitas 100 juta ton baja nasional hingga 2045 membutuhkan kebijakan pro-ekspansi, insentif fiskal, serta peran aktif BUMN dan investasi asing. Seluruh instrumen ini berpotensi diklasifikasikan sebagai “distorted subsidies” dalam terminologi OECD dan negara-negara anggota GFSEC.
Kedua, beberapa proyek ekspansi baja Indonesia ditujukan untuk pasar ekspor, khususnya ekspansi produksi stainless steel. Hal ini dapat memicu tuduhan bahwa Indonesia menjadi kontributor baru overcapacity global, apalagi jika pertumbuhan konsumsi dalam negeri tidak sejalan dengan pertumbuhan kapasitas.
Ketiga, Indonesia belum memiliki sistem pelaporan dan verifikasi kapasitas baja nasional yang seketat GFSEC. Tanpa mekanisme pelaporan yang transparan, Indonesia berisiko dinilai tidak kooperatif, dan dapat menghadapi tindakan kolektif dalam bentuk investigasi dagang, bea masuk tambahan, atau hambatan non-tarif lainnya.
Keempat, keterlibatan Indonesia dalam GFSEC secara langsung menempatkan kebijakan industri baja nasional di bawah pengawasan negara-negara anggota forum, terutama terkait pembangunan kapasitas baru. Jika strategi ekspansi Indonesia dinilai tidak selaras dengan prinsip transparansi dan pengendalian kelebihan kapasitas yang dianut GFSEC, maka Indonesia dapat menghadapi tekanan kolektif, termasuk dalam bentuk pengawasan ketat, tuduhan pelanggaran komitmen, hingga pembatasan akses pasar di negara mitra dagang utama.
Dengan demikian, Indonesia menghadapi dilema fundamental: di satu sisi ingin meraih peluang akses pasar melalui kerja sama dengan AS dan OECD, namun di sisi lain terancam kehilangan fleksibilitas untuk mengeksekusi kebijakan hilirisasi dan ekspansi industri secara mandiri.
Menyusun Arah: Langkah Strategis Indonesia dalam GFSEC
Menghadapi dilema antara komitmen dalam Global Forum on Steel Excess Capacity (GFSEC) dan kebutuhan ekspansi industri baja nasional, Indonesia perlu merumuskan strategi yang cermat, proaktif, dan realistis agar tidak terjebak dalam tekanan forum internasional yang berpotensi menghambat agenda industrialisasi nasional. Beberapa langkah yang disarankan:
Pertama, Indonesia harus memperjelas bahwa target kapasitas 100 juta ton baja nasional hingga 2045 sepenuhnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan domestik, termasuk pembangunan infrastruktur, industri otomotif, manufaktur, dan transisi energi. Dengan demikian, ekspansi ini harus dikomunikasikan sebagai respons terhadap permintaan riil dalam negeri, bukan sebagai bentuk kontribusi terhadap kelebihan kapasitas global.
Kedua, pemerintah perlu membangun sistem pelaporan kapasitas baja nasional yang transparan dan kredibel sesuai standar GFSEC, namun dengan tetap mempertahankan fleksibilitas kebijakan nasional. Transparansi ini dapat menjadi instrumen diplomatik untuk meredam kecurigaan negara lain, sekaligus menegaskan bahwa pembangunan kapasitas dilakukan secara terukur dan sah.
Ketiga, dalam merespons tekanan terhadap subsidi dan insentif industri, Indonesia perlu mengkaji ulang bentuk-bentuk dukungan fiskal yang diberikan, dan menyelaraskannya agar tidak mudah dikategorikan sebagai distorted subsidies. Model dukungan yang berbasis riset, inovasi teknologi, atau efisiensi energi sebagaimana dilakukan Jepang, bisa menjadi rujukan dalam mendesain skema yang lebih sulit diserang secara hukum dagang internasional.
Keempat, Indonesia perlu mendorong reformasi internal GFSEC agar forum ini tidak digunakan sebagai alat politik dagang negara maju, melainkan sebagai sarana dialog terbuka dan seimbang antarnegara dengan kondisi pembangunan industri yang berbeda. Untuk itu, Indonesia disarankan membangun kolaborasi strategis dengan negara-negara yang memiliki kepentingan serupa — seperti India, negara-negara ASEAN, Afrika Selatan, Brasil, dan negara berkembang lainnya — untuk memperkuat posisi tawar dalam forum. Aliansi ini penting agar GFSEC tidak menjadi forum yang hanya mencerminkan kepentingan OECD, melainkan menjadi platform yang lebih inklusif dan adil.
Kelima, Indonesia juga harus mencermati secara cermat posisi dan langkah negara-negara utama seperti China dan India dalam menjalankan atau merespons komitmen GFSEC, meskipun kedua negara tersebut bukan anggota forum ini. Dengan memahami pendekatan negara-negara tersebut, Indonesia dapat menyusun usulan kebijakan yang lebih kontekstual dan strategis, selaras dengan kebutuhan pembangunan kapasitas baja nasional. Pendekatan ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam forum, serta mencegah lahirnya standar ganda yang justru merugikan negara berkembang. Selain itu, pemahaman atas dinamika industri baja global secara menyeluruh, baik dari anggota maupun non-anggota GFSEC, akan memungkinkan Indonesia memformulasikan masukan yang lebih berimbang dan berorientasi pada pembangunan industri yang berkelanjutan.
Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat mengelola dilema secara strategis dan bahkan menjadikannya peluang untuk memperkuat posisi nasional dalam tata kelola industri baja global, sekaligus memastikan bahwa agenda hilirisasi dan ekspansi kapasitas baja tetap sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Di Balik Kesepakatan Tarif AS: Dilema Dalam Jerat Komitmen GFSEC?”, Klik untuk baca di Kompas: https://money.kompas.com/read/2025/07/30/143954626/di-balik-kesepakatan-tarif-as-dilema-dalam-jerat-komitmen-gfsec
Widodo Setiadharmaji adalah pendiri SMInsights dengan pengalaman lebih dari dua puluh tahun dalam bidang teknologi, strategi bisnis, dan pengembangan industri. Penulis artikel dinamika dan kebijakan industri yang dipublikasikan di Kompas, KataData, dan media nasional lainnya.